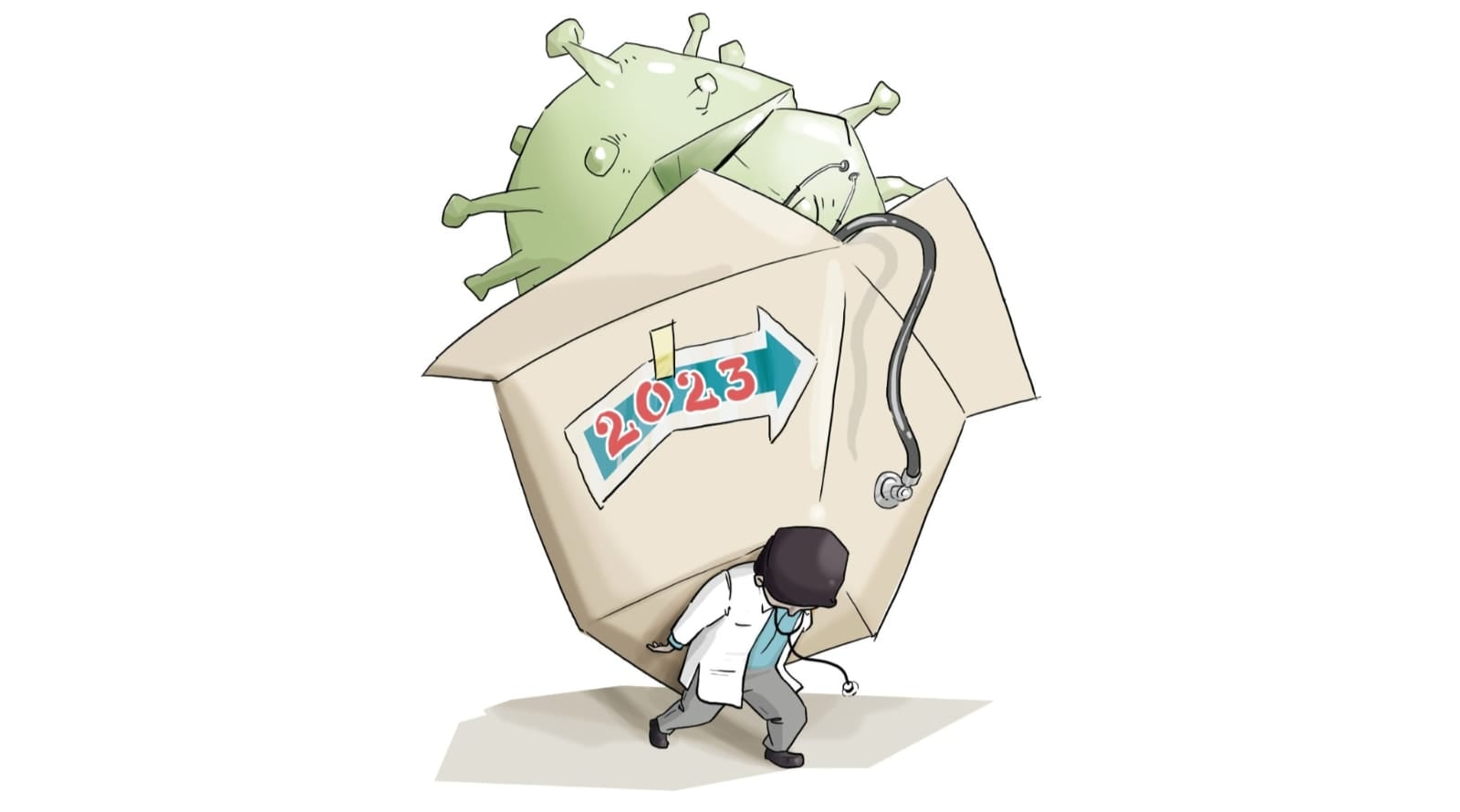Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
 Kumpulan Berita DPR RI
Kumpulan Berita DPR RI
TAHUN 2023 sudah di ambang pintu. Sejumlah analis dan lembaga internasional menyebutkan perekonomian global akan mengalami masa suram. Akan terjadi stagnasi bidang ekonomi yang berekor pada hambatan berbagai sektor, termasuk kesehatan. Apa dan bagaimana tantangan sektor kesehatan Indonesia tahun depan?
Transisi status
Setidaknya ada tiga isu kesehatan yang akan mewarnai tahun 2023. Pertama, terjadi transisi status covid-19 dari pandemi menjadi endemi. Hingga saat ini memang belum ada statement formal WHO terkait dengan transisi ini. Juga, belum ada negara yang secara formal menyatakan negerinya telah memasuki fase endemi. Namun, berbagai parameter epidemiologis serta kebijakan kesehatan berbagai negara memberi sinyal kian dekatnya fase endemi ini.
Dari sisi epidemiologis, berbagai indikator menunjukkan covid-19 memang masih belum berhenti menyebar, tetapi tingkat penyebaran dan kefatalannya sudah amat berkurang. Pada tingkat global, laju kasus covid-19 saat ini ialah 73 per 1 juta penduduk; amat rendah jika dibandingkan dengan puncak pandemi yang mencapai 431 per 1 juta penduduk. Case fatality rate (CFR), yang merupakan indikator kefatalan kasus, juga sudah sangat berkurang.
Saat ini, CFR hanya berkisar 0,33%. Artinya, dari 1.000 orang yang terkonfirmasi positif, hanya 3 orang yang meninggal. Ini sangat rendah ketimbang CFR saat awal-awal pandemi yang sempat mencapai 8%. Kemampuan virus untuk menginfeksi orang lain, yang biasa dinyatakan sebagai reproduction rate, pun sudah menurun dari level 2,0-3,0 menjadi 1,0.
Saat bersamaan, makin banyak orang terproteksi dengan vaksin covid-19. Sekitar 69% penduduk dunia telah mendapat vaksin saat ini; 63% memperoleh vaksin lengkap dan sisanya masih parsial. Parameter-parameter itu menjadi sinyal penurunan kapasitas infeksi dan penyebaran serta di saat yang sama terjadi peningkatan kekebalan terhadap covid-19.
Di Indonesia, laju kasus telah menurun hingga 5,6 per 1 juta penduduk; amat rendah jika dibandingkan dengan saat puncaknya yang melebihi 200 kasus per 1 juta penduduk. CFR telah menukik hingga 0,8%, jauh ketimbang ketika puncaknya yang melebihi 7%. Reproduction rate sudah mencapai 0,57, artinya virus ini tidak lagi menginfeksi orang lain. Meski positive rate masih bertengger di atas 8%, levelnya jauh lebih baik daripada saat puncak yang melebihi 33%. Lebih dari 73% populasi Indonesia juga telah mendapat vaksin covid-19. Sebanyak 63% di antaranya mendapat vaksinasi lengkap.
Di lapangan, fenomena menuju endemi juga sudah mulai tergambar. Berbagai negara telah menghentikan penggunaan masker serta keharusan menunjukkan status vaksinasi saat menghadiri acara. Pada pesta sepak bola Piala Dunia 2022 di Qatar baru-baru ini, tidak ada lagi penggunaan masker, tes RAT/PCR, dan penunjukan status vaksinasi. Setiap pertandingan dihadiri oleh puluhan ribu penonton tanpa masker. Total, jutaan penonton menghadiri 36 pertandingan tanpa restriksi sama sekali. Di Arab Saudi, ibadah umrah tidak memerlukan lagi penggunaan masker, tes covid-19, dan status vaksinasi. Padahal yang berumrah jumlahnya jutaan. Tidak adanya restriksi pada dua event besar ini setidaknya menjadi sinyal positif kian dekatnya fase endemi.
Meski Indonesia akan memasuki masa endemi di tahun 2023, bukan berarti pekerjaan sektor kesehatan akan menjadi ringan. Status endemi justru mengisyaratkan bahwa covid-19 akan tetap ada meski ‘magnitudonya’ tidak sedramatis saat pandemi. Status ini sama dengan status sejumlah penyakit yang telah berada pada fase endemi saat ini, seperti tuberkulosis, malaria, dan HIV/AIDS. Mereka tetap ada dengan tingkat morbiditas dan mortalitas tertentu.
Untuk mengantisipasi fase endemi covid-19, pemerintah perlu mempersiapkan program berorientasi endemi. Di antaranya, pengadaan dan penyuntikan vaksinasi covid-19 secara reguler, peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk pencegahan resurgence, dan mempersiapkan sarana dan prasarana bila sewaktu-waktu terjadi peningkatan kasus dan kematian secara signifikan. Program endemi bukan program sederhana dan ringan meski masyarakat telanjur menganggap endemi sebagai kondisi ringan dari pandemi.
Kedua, setelah lebih dua tahun didera pandemi, banyak persoalan kesehatan lain di Indonesia yang membutuhkan penanganan segera. Selama pandemi, fokus kesehatan diarahkan kepada penanggulangan covid-19, yang akhirnya banyak program kesehatan lain terbengkalai. Sejak pandemi, cakupan imunisasi dasar menurun dari 84,2% menjadi 79,6%. Kekurangan cakupan ini mesti dikejar segera. Dalam beberapa tahun terakhir, prevalensi stunting hanya menurun 3,3%. Padahal target tahun 2024 ialah 14%. Jumlah kematian akibat tuberkulosis tahun 2021 masih lebih dari 90 ribu. Ini sangat perlu diturunkan.
Isu-isu ini krusial karena merupakan parameter dasar keberhasilan kesehatan suatu negara. Sebagian malah termasuk target Sustainable Development Goals (SDG) yang mesti dicapai. Bila isu itu tidak diselesaikan, akan timbul image negatif tentang perkembangan kesehatan Indonesia. Indonesia akan dianggap tidak berhasil dalam pembangunan kesehatan. Tahun 2023, semua isu itu mesti mendapat perhatian pemerintah. Bila tidak dapat mencapai target standar yang telah ditetapkan, paling tidak pemerintah dapat memperbaiki profil parameter yang ada. Jangan berbicara program kesehatan muluk-muluk bila persoalan kesehatan dasar tidak tercapai dengan baik.
Data, sarana, dan tenaga kesehatan
Ketiga, Kementerian Kesehatan telah menggagas program transformasi bidang kesehatan yang akan mulai diimplementasikan pada 2023. Program ini akan menyasar enam pilar, yaitu layanan primer, layanan sekunder, sistem pelayanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia, dan teknologi kesehatan. Program ini terdengar sangat menarik dan menggiurkan. Namun, untuk mulai mengimplementasikannya pada 2023 kelihatannya akan berhadapan dengan banyak kendala. Pasalnya, negeri ini masih memiliki sejumlah persoalan kesehatan serius yang perlu diprioritaskan sebelum mengimplementasikan program lain. Di antara persoalan serius tersebut ialah kesenjangan tiga aspek, yakni data, sarana kesehatan, dan tenaga kesehatan.
Terkait dengan kesenjangan data, hingga kini data kesehatan Indonesia belum seragam. Masih terdapat perbedaan data kesehatan antara institusi yang satu dan yang lain. Perihal jumlah dokter di Indonesia saja, ada perbedaan antara Kemenkes, Kolegium Kedokteran Indonesia, dan IDI. Kemenkes menyebut jumlah dokter saat ini sekitar 130 ribu, sedangkan KKI dan IDI menyebutnya masing-masing 178 ribu dan 200 ribu. Data mengenai tenaga kesehatan lain juga sangat berbeda antarinstitusi.
Kesenjangan data itu membuat lembaga kesehatan internasional tidak sepenuhnya mengandalkan data kesehatan Indonesia. Pada setiap program dan perencanaan, lembaga internasional lebih memilih menggunakan data mereka. Indonesia sangat perlu memiliki metadata kesehatan yang akurat, valid, dan terintegrasi. Tanpa data yang adekuat, sangat sulit merencanakan dan menjalankan program secara tepat. Tanpa data adekuat, upaya transformasi kesehatan hanya akan melahirkan program yang tidak tepat dan salah sasaran.
Selain kesenjangan data, Indonesia juga mengalami kesenjangan sarana kesehatan, terutama sarana pelayanan kesehatan primer. Sebagian daerah memiliki beberapa puskesmas di wilayahnya, sementara daerah lain tak memiliki puskesmas sama sekali. Secara nasional, terdapat lebih dari 10 ribu puskesmas. Akan tetapi, penyebaran dan kualitas pelayanannya masih sangat jomplang antara satu dan lain. Masih banyak puskesmas yang tidak memiliki alat kesehatan standar.
Di NTB, pada 2020, hampir 40% puskesmas belum memiliki alat kesehatan standar. Selain itu, tenaga kesehatan, terutama dokter, juga tidak terdistribusi dengan baik. Maladistribusi dokter adalah persoalan klasik kesehatan sejak beberapa dekade lampau dan hingga kini belum terselesaikan. Hingga saat ini, masih terdapat jurang lebar terkait dengan jumlah dan rasio dokter tiap daerah.
Per 2020, di DKI Jakarta 1 dokter hanya menangani 680 penduduk, sedangkan di Sulawesi Barat 1 dokter menangani 10.417 penduduk. Jadi beban yang dihadapi dokter di Sulawesi Barat 15 kali lipat daripada dokter di Jakarta. Ini perbedaan beban yang sangat besar. Maladistribusi dokter spesialis juga sama. Di DKI terdapat 52 dokter spesialis untuk setiap 100.000 penduduk, sedangkan di Papua hanya tersedia 3 dokter spesialis untuk 100.000 penduduk. Akibat maladistribusi ini, hingga saat ini sekitar 5% puskesmas masih belum memiliki dokter sama sekali dan 9% memiliki dokter tapi dokternya tinggal jauh dari puskesmas.
Kemampuan pelayanan puskesmas pun amat berbeda. Ada beberapa puskesmas yang telah dilengkapi oleh beberapa dokter spesialis dan siap memberikan pelayanan kesehatan, khususnya terkait 144 jenis penyakit yang dapat ditangani pada tingkat puskesmas. Namun, masih banyak puskesmas yang memiliki dokter baru lulus, yang karena keterbatasan sarana dan prasarana, belum dapat memberikan pelayanan kesehatan dasar. Ini membuat kualitas layanan bervariasi dari satu daerah ke daerah lain.
Segera ditangani
Adanya kesenjangan data, sarana, dan tenaga kesehatan ini membuat program transformasi kesehatan akan mengalami hambatan serius. Penyelesaian kesenjangan ini perlu dilakukan pada 2023 sebelum meluncurkan program lain yang lebih komprehensif.
Meski pandemi akan bertransisi menjadi endemi tahun depan, bukan berarti beban bidang kesehatan akan menjadi ringan. Berbagai persoalan dasar tapi krusial perlu segera ditangani sebelum meluncurkan program yang lebih komprehensif, termasuk transformasi bidang kesehatan. Bila tidak, besar kemungkinan program ini terkendala serius atau bahkan mengalami kegagalan implementasi.
Malaria masih menjadi masalah kesehatan global yang kompleks akibat imunitas parsial, pembawa asimtomatik, dan resistensi insektisida.
MEDIAINDONESIA.COM, 8 Februari 2026, menurunkan berita berjudul ‘Lebih Awal, Arab Saudi Mulai Terbitkan Visa Haji 2026 Hari Ini’.
PENINGKATAN keamanan pangan membutuhkan kebijakan yang tepat demi mewujudkan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang lebih baik di masa depan.
Jika langkah-langkah pencegahan dan deteksi dini tidak diperkuat sejak dini, jumlah kasus kanker diprediksi akan meningkat hingga 70% pada 2050.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
INDONESIA turut ambil bagian dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Muslim Youth Summit (ASEAMYS) 2026 yang digelar di Brisbane Technology Park, Australia, pada 6-7 Februari 2026.
Thomas Djiwandono mengusulkan agar pemerintah dan bank sentral meninggalkan skema burden sharing yang diterapkan pada masa pandemi covid-19.
Melihat ancaman besar terhadap keberlanjutan layanan kesehatan dasar, dr. Harmeni mendirikan Symptomedic, platform telemedisin dan layanan pengantaran obat.
ANCAMAN kesehatan global kembali muncul dari Tiongkok. Setelah virus corona yang menyebabkan pandemi covid-19, kali ini virus baru influenza D (IDV) ditemukan.
Sengketa gaji Cristiano Ronaldo dengan Juventus terkait penundaan pembayaran saat pandemi covid-19 masih berlanjut. Putusan arbitrase dijadwalkan 12 Januari 2026.
Teknologi vaksin mRNA, yang pernah menyelamatkan dunia dari pandemi covid-19, kini menghadapi ancaman.
Menteri Kesahatan AS Robert F. Kennedy Jr. membuat gebrakan besar dengan mencabut kontrak dan membatalkan pendanaan proyek vaksin berbasis teknologi mRNA, termasuk untuk covid-19.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved