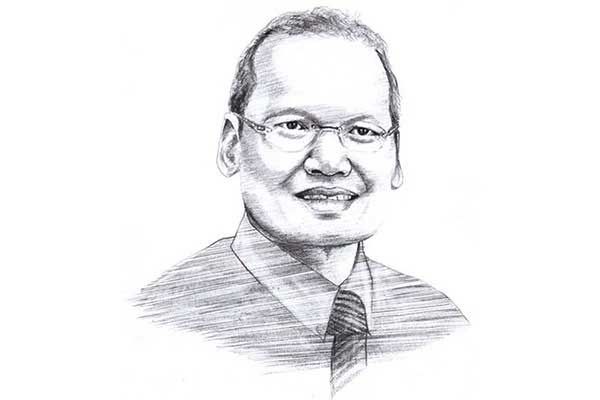Headline
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
 Kumpulan Berita DPR RI
Kumpulan Berita DPR RI
WARGA positif korona terus bertambah menembus angka 95 ribu. Hal itu terjadi pekan lalu. Penyebabnya, warga tak disiplin menaati protokol kesehatan.
Benarkah? Maaf, barangkali kita tidak mengenal masyarakat kita. Meminjam sebuah ekspresi, “Kita tak dapat menemukan kaki-kaki kita bersama mereka.”
Kaki tidak diciptakan untuk tegak di awang-awang. Kaki kursi tegak di lantai. Kaki meja pun demikian. Kaki manusia tegak di bumi. Bahkan berjejak. Adakah jejak kita bersama masyarakat? Barangkali kita tak menemukannya, karena kaki-kaki kita tak bersama mereka.
Suatu hari ada warga merebut jenazah korban korona dari dalam peti mati di sebuah ambulans. Jenazah hendak dibawa ke permakaman. Apa makna peristiwa ini? Kiranya jauh ‘melampaui’ disiplin kepatuhan pada protokol kesehatan.
Barangkali di situ bersemayam ketidakpercayaan bahwa jenazah telah diperlakukan sesuai kewajiban agama. Jenazah direbut untuk dibawa ke rumah, dimandikan, dikainkafani, disembahyangi, dan penuh keikhlasan menguburnya.
Apakah mereka yang merampas jenazah tak takut mati tertular korona dari yang mati? Pertanyaan ini pun kiranya pertanda barangkali kita tidak mengenal masyarakat kita.
Orang bijak bilang untuk mengerti kematian, Anda butuh mengerti kehidupan. Perbuatan merebut jenazah kiranya menunjukkan penger-
tian yang berbeda, yang sebaliknya. Untuk mengerti kehidupan, Anda butuh mengerti kematian. Pengertian yang barangkali tidak kita kenal hadir di tengah masyarakat kita.
Suatu hari menjelang Lebaran orang dilarang mudik. Mudik dalam pengertian pulang ke kampung halaman. Ribuan orang melanggarnya. Apakah mereka tak tahu perihal larangan itu? Tahu. Pulang kampung di kala Lebaran ialah ritual kultural yang tak bisa lain harus dijalani. Bukankah gara-gara ritual itu dapat menyebarkan korona ke kampung halaman? Kenapa nekat? Lagi ini pertanyaan yang menunjukkan barangkali kita tidak mengenal masyarakat kita.
Di dalam hidup kita sehari-hari ‘melarang’ kiranya lebih mudah daripada ‘menegakkan larangan’. Di sebuah tempat ‘Dilarang Merokok’, ada saja orang merokok di situ. Pelakunya bukan buta aksara, bukan pula buta simbol.
Merokok bukan pula perkara substansial, yakni ritual kultural atau ritual kepercayaan, yang bila tak dilakukan menyebabkan orang seperti berutang kepada sebuah tradisi. Lalu bagaimana menjelaskan, anak bangsa ini begitu patuhnya pada larangan merokok ketika berada di Singapura?
Barang kali bukan hanya kita tidak mengenal masyarakat kita. Kita pun tidak mengenal kita. Tak mengenal ‘kita’ kiranya membuat ‘kita’ mudah membuat ‘proyeksi’ untuk ‘mereka’. Setelah PSBB diberlakukan, suatu hari (5 Juni 2020), Gubernur DKI Jakarta memutuskan masa transisi. Empat belas hari kemudian (19 Juni), transisi itu menjadi transisi kedua. Empat belas hari setelah itu (2 Juli), transisi kedua diperpanjang lagi menjadi transisi ketiga. Lalu, 14 hari setelahnya (17 Juli), diperpanjang lagi menjadi transisi keempat.
Alasannya, warga positif korona bertam- bah banyak. Dalam hal ini ada dua perkara. Pertama, kita tidak mengenal masyarakat kita. Kedua, pembuat kebijakan pun tidak mengenal ‘kita’ (dalam mengumumkan masa transisi, Gubernur Jakarta selalu menggunakan kata ‘kita’).
Dalam hal yang pertama, barang kali ‘transisi’ diartikan sebagai ‘pelonggaran’. Arti yang bisa jauh sekali penerapannya. Di dalam masyarakat yang lebih mudah melarang daripada menegakkan larangan, kiranya ‘pelonggaran’ bersaudara dekat sekali dengan ‘kebebasan’.
Lihatlah warga yang mengenakan masker. Masker itu melindungi dagunya, bukan melindungi mulutnya, bukan pula hidungnya--dua organ pernapasan tempat masuknya korona.
Hal yang kedua, pembuat kebijakan ialah kita yang tidak mengenal kita. Siapa pun pemimpin yang dipilih rakyat, kiranya mengandung pengertian ‘dari kita untuk kita’ yang dicerminkan melalui kebijakannya. ‘Transisi’ mengandung makna ‘bersifat sementara’. Asal kata itu ialah ‘transition’ (Latin), antara lain bermakna ‘penyeberang an (ke pihak lain)’.
Inilah penyeberangan yang sifatnya sementara dari pandemi ke kehidupan yang normal. Yang terjadi ialah bukan penyeberangan, melainkan berjalan di tempat bahkan mundur.
Kita memang bukan penganut kebijakan garis keras prokesehatan publik. Kita memadukan kebijakan prokesehatan dan propemulihan ekonomi. Kebijakan ‘transisi’ ialah kebijakan bermaksud mulia yang mengandung pesan jika kita disiplin pakai masker, disiplin jaga jarak, disiplin cuci tangan dengan sabun, kita bakal sampai ke ‘seberang’, yakni tubuh kita sehat, pun ekonomi kita. Akan tetapi, inilah kemuliaan di atas asumsi bahwa kita mengenal masyarakat kita. Kenyataannya, ‘kita tak dapat menemukan kaki-kaki kita bersama mereka’.
Suatu hari, Presiden bersuara keras. Katanya, uang pemerintah daerah di bank masih ada Rp170 triliun. Dalam resesi belanja, pemerintah berperan sangat penting menggerakkan perekonomian. Kok, masih ada pemerintah daerah yang tak satu perasaan dengan kita? Bukankah kepala daerahnya dipilih oleh ‘kita’, yakni rakyat setempat?
Pertanyaan itu pun lagi-lagi menunjukkan kita tidak mengenal masyarakat kita. Kita pun tidak mengenal pemimpin kita. Sesungguhnya ‘kita tak dapat menemukan kaki-kaki kita bersama mereka’.
KEMENTERIAN Pariwisata (Kemenpar) kembali menegaskan pentingnya penerapan protokol kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan (CHSE) di tempat wisata.
Dalam menghadapi ancaman Covid-19 ini, Pemko Banjarmasin mulai melakukan mitigasi dengan melibatkan semua sektor.
KETUA Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene menilai lonjakan kasus covid-19 saat ini harus menjadi peringatan penting bagi pemerintah dan masyarakat.
KEPALA Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, mengimbau masyarakat Indonesia untuk kembali menerapkan protolol hidup sehat menyusul lonjakan kasus Covid-19
Sejulah atlet yang berkompetisi di Olimpiade Paris 2024 terjangkit Covid-19. Terbaru, perenang Inggris Adam Peaty dinyatakan positif setelah lima atlet polo air Australia.
Janji kampanye Ganjar terkait 1 nakes 1 desa dianggap tidak cukup penuhi kebutuhan layanan kesehatan
Thomas Djiwandono mengusulkan agar pemerintah dan bank sentral meninggalkan skema burden sharing yang diterapkan pada masa pandemi covid-19.
Melihat ancaman besar terhadap keberlanjutan layanan kesehatan dasar, dr. Harmeni mendirikan Symptomedic, platform telemedisin dan layanan pengantaran obat.
ANCAMAN kesehatan global kembali muncul dari Tiongkok. Setelah virus corona yang menyebabkan pandemi covid-19, kali ini virus baru influenza D (IDV) ditemukan.
Sengketa gaji Cristiano Ronaldo dengan Juventus terkait penundaan pembayaran saat pandemi covid-19 masih berlanjut. Putusan arbitrase dijadwalkan 12 Januari 2026.
Teknologi vaksin mRNA, yang pernah menyelamatkan dunia dari pandemi covid-19, kini menghadapi ancaman.
Menteri Kesahatan AS Robert F. Kennedy Jr. membuat gebrakan besar dengan mencabut kontrak dan membatalkan pendanaan proyek vaksin berbasis teknologi mRNA, termasuk untuk covid-19.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved