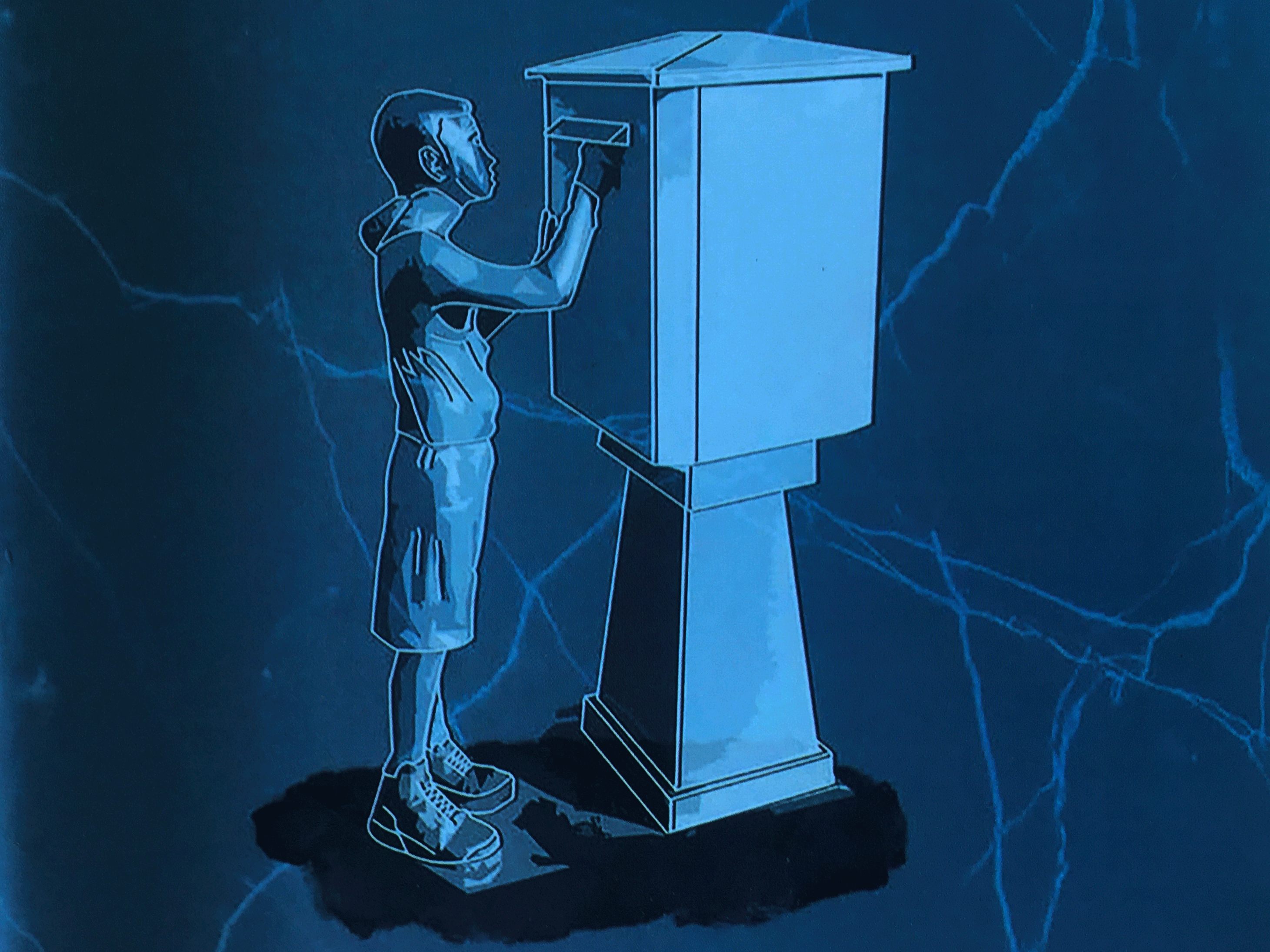Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
 Kumpulan Berita DPR RI
Kumpulan Berita DPR RI
MEMBACA buku kumpulan puisi berjudul Puisi dari Lima Benua karya Emji Alif membawa kita seakan sedang berada di negara-negara berbeda. Ada sebuah benang merah bahwa puisi perjalanan bukan sekadar ditulis, namun harus dialami dengan mata kepala sendiri.
Emji, seorang pesastra dan dosen di Universitas Indonesia. Ia piawai mengabadikan setiap kenangan yang didapatkannya dari berbagai negara. Runut waktu penulisan puisi-puisi pun dilakukannya sejak 1985 lewat puisi berjudul Yosemite, New York City, dan Kyoto, sampai puisi berjudul Budapest (2009) dan Lapangan Merah pada 2019.
Menarik untuk melihat kembali sejarah, terutama pelayaran bangsa Eropa ke Nusantara di abad-abad silam. Mereka selalu menuliskan catatan-catatan penting, baik fiksi maupun nonfiksi. Mereka juga menggambar dan melukis setiap objek yang dinilai menarik di setiap pulau yang disinggahi untuk kebutuhan ilmu pengetahuan.
Emji pun demikian juga melakukan pelawatan. Dalam setiap tempat yang dikunjungi, ia abadikan lewat puisi realisme. Umumnya, gaya ini mengusung kebenaran absolut, menurut subjek atau sudut pandang setiap penulis. Pasalnya, mereka mengalami, melihat, dan merasakan sendiri adat istiadat, bahasa, dan budaya baru di negeri seberang.
Nah, memang perlu untuk melihat kembali perjalanan Emji lewat kumpulan puisi terbarunya tersebut. Ia menentukan satu per satu peristiwa pelawatan secara sistematis. Ia tak sekadar melihat, namun menuangkan objek pengembaraan secara alamiah sebagai sebuah kemampuan menghadirkan puisi-prosais.
Buku antologi Puisi dari Lima Benua ini diterbitkan oleh Pentas Grafika, Jakarta (2022) dan memuat 58 karya. Masing-masing puisi mengusung kisah yang berbeda-beda. Memiliki pesan dan kesan yang menggugah perasaan pembaca jika dikaji secara lebih mendalam. “Kami menerbitkan buku ini sebab mengusung puisi perjalanan yang menarik. Sebelumnya, kami juga telah menerbitkan karya sastrawan Putu Wijaya,” papar Cita Moralis, Pengelola Pentas Grafika.
Buku Emji dapat menjadi pilihan bacaan alternatif. Karya-karyanya cukup khas. Tengok saja sebuah karya berjudul Acropolis (hlm 42). Berikut petikannya. Di Bari, angin menerbangkan karcis ke laut: ferry segera bertolak ke Yunani// Bayu mengembangkan layar dan perahu bergegas mengejar angan-angan// Poseidon mencacah lautan menciptakan gelombang yang berkejar-kejaran// Fajar baru telah muncul menyinari sebuah bukit dan langkah menjadi tertahan// Di puncaknya Acropolis/ kuil dewa-dewa bermandi cahaya pagi// Meskipun terlanjur renta tak juga kehilangan pesonanya//.
Di tempat dewa-dewa memperlihatkan kehadirannya/ kuil-kuil didirikan// Jauh sebelum nabi-nabi dilahirkan para pelaut tak berdaya menghadapi taifun gelombang pasang dan gempa bumi// Poseidon pun menjadi dewa yang ditakuti di laut Aegea/ Theseus sang pembunuh Minotaur dilahirkan/ dan harapan bagi kemerdekaan pun bersemi//.
Melalui doa-doa yang dipanjatkan dan pengorbanan yang dilakukan di kuil-kuil suci// Juga bagi Erechtheus sang pemimpin kota/ dan Dewi Athena pelindung alam dan kesuburan// "Bukannya dewa-dewa sudah dikubur, dan kuil-kuil itu telah hancur," katamu mendebat seperti biasa// "Bisa jadi," jawabku. Tapi setidaknya kita tahu//.
Membaca puisi Acropolis di atas memberikan penggambaran tentang pengalaman Emji di sebuah pelabuhan tua. Ia mencoba untuk berbagi kenangan kepada pembaca. Disajikan secara deskriptif, sederhana, dan mudah dipahami. Puisi ini disajikan secara prosais sehingga enak dibaca. Membawa kita terlena ke dalam perasaan yang disajikannya.
Pada puisi lain, Emji juga hadirkan perspektif yang unik pula. Ia suguhkan peristiwa sejarah perihal Perang Salib hingga Perang Dunia ke-2 di Benua Biru. Latar belakang sungai Danube di Budapest, Hungaria, misalnya, begitu tersaji jelas dalam bait demi bait. Puisi itu dijuduli Budapest (hlm 56), terdiri dari dua alinea, dan disajikan secara prosais.
Berikut petikan puisi tersebut. (1) Di dunia atas dewa-dewa bersemayam: Isten dan Ordog// Dan ketika mereka datang ke halaman taman/ rerumputan menggigil// Namun burung-burung yang sadar bangkit dari jalinan rumput liar// Mengibaskan sayap dan terbang tinggi/ memikul kesedihan tak terperi// Ketika kejahatan dan kebenaran bertarung, hanya sayap-sayap kuat yang mampu menerobos cakrawala baru//.
(2) Di depan gedung parlemen yang istimewa/ sungai Danube mengalir// Aku melangkah menyusuri tepi sungai memungut semua kenangan// Sultan Sulaiman membawa bala tentaranya ke tempat ini/ begitu pula dengan Hitler// Perang selalu membawa maut dan kenangan buruk// Di sisi sungai masih tersisa sepatu-sepatu korban yang terbunuh oleh Nazi/ hanya karena mereka Yahudi//.
Jika saya melihat secara lebih jeli, maka Sulaiman dalam puisi di atas merujuk kepada Sulaiman the Magnificent, salah satu sultan Ottoman yang paling hebat. Ia meninggal di Szigetvar, Hungaria pada 1566. Organ internalnya dimakamkan di Szigetvar, tetapi tubuhnya dibawa kembali ke ibu kota Ottoman, Istanbul untuk dimakamkan secara tradisional.
Putra Sulaiman, Sultan Selim II, membangun sebuah makam untuk ayahnya di Szigetvar dan sebuah kompleks megah di sekitarnya. Sayang, makam dan kompleksnya hilang ketika Hungaria jatuh ke tangan Austria pada akhir abad ke-17. Tinggal puing-puing yang kini dijadikan lokasi penelitian antropolog, kulturolog, dan sejarawan dunia.
Memang, puisi Budapest tidak begitu terperinci, namun itulah puisi memiliki makna multitafsir bagi setiap pembaca yang heterogen. Meski demikian, Emji berhasil menghadirkan unsur keakuannya lewat alinea kedua yang berbunyi; ‘Aku melangkah menyusuri tepi sungai memungut semua kenangan’. Itu jelas berbicara tentang sejarah kota Budapest.
Pelesir di Eropa Timur tidaklah lengkap jika belum mengunjungi Moskwa, Rusia.
Emji tahu benar hal itu sehingga ia menuliskan puisi perjalanannya tentang pesona Lapangan Merah pada 2019 silam. Setiap observasi dan pendekatan mata batinnya tertuju kepada bangunan bersejarah yang ada di sekitar Kremlin. Mulai dari gereja, pusat perbelanjaan modern, hingga Kremlin, istana megah tempat Presiden Vladimir Putin, berkantor.
Tengok saja puisi berjudul Lapangan Merah (hlm 10) berikut ini. Lenin/ Stalin/ Khrushchev/ Gorbachev/ Putin// Kremlin tak pernah sama// Tokoh-tokoh itu samar-samar kita ingat/ mungkin pula tercatat di sejarah// Pemimpin telah datang dan pergi/ suatu bangsa akan terus berubah// For Right or Wrong// Tak ada yang abadi// Kecuali gereja ortodoks St. Basil di Lapangan Merah// Gereja bawang berwarna-warni itu tetap tak berubah// Wisatawan masih berpose dengan bermacam ragam gaya di hadapannya//.
Beberapa langkah dari sana/ Kremlin menutup diri dengan pagar-pagar tinggi// Komunisme telah mati/ tapi banyak orang tidak percaya// Setiap bulan September mereka selalu mengganggu pesta ulang tahunku// Padahal seharusnya mereka tahu/ Lenin dan Stalin sudah lama dikubur//.
Tak sepelemparan batu dari Kremlin/ GUM toko serba-ada berarsitektur cantik berusia lebih satu abad menjual 100 jenama internasional terkemuka// Lima puluh tahun silam/ warga masih berbaris panjang di Lapangan Merah berharap mendapat barang-barang konsumsi// Kini hanya dompet di kantong yang menjadi limitasi// GUM bukan lagi milik pemerintah/ tapi dikelola swasta// "Bukankah itu sebuah kuasa kapitalis?" katamu mengedipkan mata//.
Masih sepelemparan batu dari Kremlin/ Okhotny Ryad sebuah shopping mall bawah tanah telah berdiri// Di dalamnya semua jenama internasional boleh dipilih// Di depan tempat belanja itu berdiri Hotel Four Season/ jaringan hotel Amerika// Tiba-tiba aku ingin menyimpulkan: Meskipun tak pernah akur/ komunisme agaknya tak mungkin dikalahkan agama/ tapi dengan semangat berbelanja// "Jenama yang menggoda, shopping, discount atau sale selalu lebih asyik," katamu sambil menyeruput kopi Starbucks di beranda Hotel Four Season, Moskwa//.
Buku antologi Puisi dari Lima Benua sangat penting dalam perjalanan perpuisian Emji. Ini cocok bagi para pembaca yang sedang berencana untuk melakukan pelesir ke negara-negara seperti Jepang, Malaysia, hingga Rusia. Puisi-puisi di buku ini dapat menjadi semacam sebuah guide book atau buku panduan wisata.
Di sisi lain, antologi ini dapat pula sebagai perangsang wisatawan agar menjadikan mata hati untuk menangkap dan mengabadikan perjalanan mereka lewat karya sastra. Buku ini laik dibaca karena mengusung pesan sejarah dan budaya berbeda dari tempat-tempat yang menarik dan unik di dunia. Biarkanlah puisi-puisi serupa terus terposkan dari negeri seberang. (SK-1)
Baca juga: Sajak Kofe, Warung Puisi Pascakontemporer Indonesia
Baca juga: Fatamorgana Gotabaya Rajapaksa
Baca juga: Membaca Ibu, Puisi, dan Kopi
 Iwan Jaconiah adalah penyair, editor puisi Media Indonesia, dan penulis buku Hoi!, sebuah kumpulan puisi tentang kisah diaspora Indonesia di Rusia.
Iwan Jaconiah adalah penyair, editor puisi Media Indonesia, dan penulis buku Hoi!, sebuah kumpulan puisi tentang kisah diaspora Indonesia di Rusia.
Dalam pandangan Gol A Gong sastra berfungsi sebagai ruang jeda dari banjir informasi digital yang dangkal.
SAYEMBARA Novel DKJ 2025 telah mengumumkan pemenangnya semalam, Rabu, (5/11) di Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat.
Temukan kata kata estetik penuh makna! Koleksi ungkapan indah, puitis, dan inspiratif untuk jiwa yang mendalam.
Bangun cerita inspiratif! Pelajari struktur narasi yang menggugah, raih hati pembaca, dan sebarkan pesan bermakna melalui alur cerita yang kuat.
Gadis Kretek: Novel Indonesia memikat! Selami kisah cinta, ambisi, dan warisan kretek yang kaya. Baca ulasan lengkapnya sekarang!
Temukan puisi pendek sekolah penuh cinta pendidikan. Ungkapkan rasa, kenangan, dan semangat belajar melalui kata-kata indah.
Dalam pandangan Gol A Gong sastra berfungsi sebagai ruang jeda dari banjir informasi digital yang dangkal.
SAYEMBARA Novel DKJ 2025 telah mengumumkan pemenangnya semalam, Rabu, (5/11) di Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat.
Kemendikdasmen melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) menegaskan komitmen negara terhadap pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa serta sastra.
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), menggelar rangkaian kegiatan strategis dalam rangka penguatan literasi dan sastra, serta revitalisasi bahasa daerah di Jawa Tengah.
Aprinus mencontohkan, beberapa karya yang kandungan SARA, yakni pada novel Salah Asuhan yang pada draf awalnya disebut menyinggung ras Barat (Belanda).
Sastra sebagai suatu ekspresi seni berpeluang mempersoalkan berbagai peristiwa di dunia nyata, salah satunya adalah persoalan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved