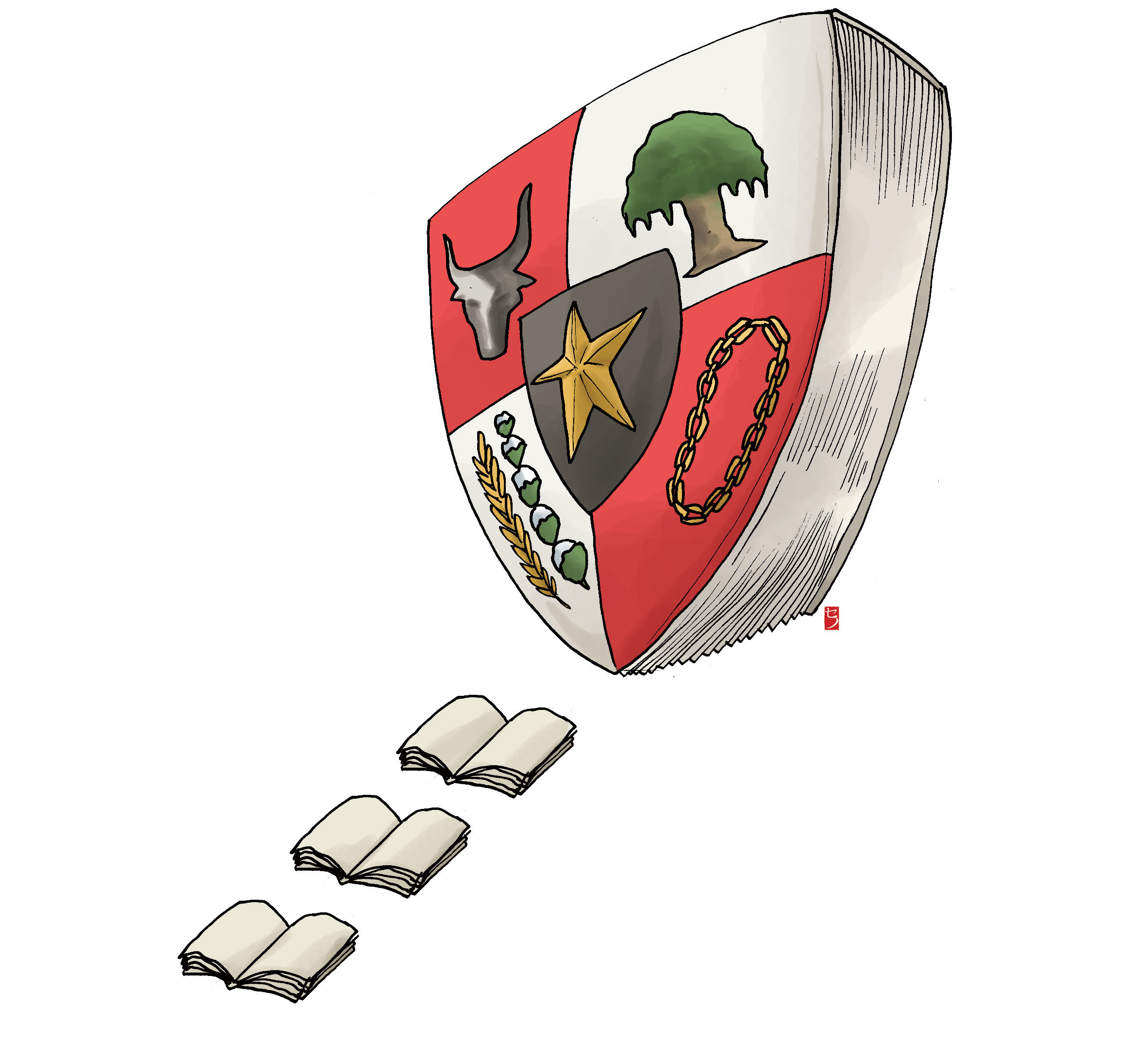Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
 Kumpulan Berita DPR RI
Kumpulan Berita DPR RI
"Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu, hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya". (Ki Hajar Dewantara)
NASIHAT tokoh pendidikan nasional itu memang benar adanya. Bahwa puncak penemuan jadi diri manusia bukanlah pada tingginya jenjang pendidikan yang diraih. Bukan pula harta yang berlimpah terlebih status sosial yang melangit, melainkan kebermanfaatan diri bagi lingkungan.
Sejalan dengan itulah pendidikan juga mengarah pada kebermanfaatan diri bagi masyarakat. Cita-cita luhur itu tertuang pula dalam konstitusi dan perundang-undangan. Baca saja pada Pasal 31 ayat 5 UUD 1945, secara tegas memberi sinyal bahwa pemerintah berupaya memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan.
Luhurnya tujuan pendidikan tersebut tak pantas terlupakan dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia. Apalagi menggesernya dengan dalih arus globalisasi. Sikap pemerintah yang terlalu fokus pada pencapaian prestasi internasional pada lingkup pendidikan tinggi cenderung diukur dalam kuantitatif semata.
Kerja pemerintah yang cenderung mencaplok pendekatan luar negeri dalam mendorong kemajuan pendidikan di Indoensia terkesan tanpa arah--jika tak ingin disebut ekstrem--. Lihat saja begitu semangatnya membawa guru asing, kurikulum asing hingga rektor asing sebagai langkah mempercepat laju keberhasilan pendidikan.
Sedikit mengutip sindiran filsuf Plato yang menilai pendidikan sebagai upaya mewujudkan suatu negara yang ideal. Yakni pendidikan yang membebaskan dan memperbaharui serta lepas dari belenggu ketidaktahuan dan ketidakbenaran. Hal senada disampaikan pula filsuf Aristoteles bahwa tujuan pendidikan haruslah sama dengan tujuan akhir dari pembentukan negara yang harus sama pula dengan sasaran utama pembuatan dan penyusunan hukum serta harus pula sama dengan tujuan utama konstitusi, yaitu kehidupan yang baik dan berbahagia.
Pemikiran itu sejalan dengan pemikiran KI Hajar Dewantara yang menitikberatkan pendidikan sebagai upaya meningkatkan kebermanfaatan manusia. Bukan sebaliknya, pendidikan menjadikan manusia kehilangan kendali terhadap diri dan lingkungan.
Pendidikan tinggi dan kebinekaan
Pendidikan tinggi di Indonesia memang dirancang sedemikian unik. Berbeda dengan negara-negara lain. Pendidikan Tinggi di Indonesia berusaha memainkan peran Tri Dharmanya, yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Sebuah pola yang tidak dilakukan pada pendidikan tinggi di negara lain.
Keunikan lain dari pendidikan tinggi di Indonesia ialah asas kebinekaan. Suatu nilai kehidupan yang tumbuh dalam pribadi bangsa Indonesia. Tidak banyak negara yang memiliki kemajemukan sehebat Indonesia. Maka kemajemukan itu harus terjaga dalam setiap gerak berbangsa dan bernegara, termasuk persoalan pendidikan bangsa ini.
Asas kebinekaan dalam pendidikan tinggi tertuang pada Pasal 3 huruf (h) UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Asas kebinekaan memberi tekanan yang khas dalam pendidikan tinggi di Indonesia. Penempatan asas kebinekaan sejatinya wujud nyata untuk menghidupkan roh kebangsaan dalam pendidikan. Asas kebinekaan menjadi fundamental nilai interaksi sosial bagi generasi bangsa demi sebuah tujuan tercapainya kehidupan Indonesia yang utuh.
Survei Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tahun 2018 memperlihatkan persoalan kebinekaan yang belum tuntas. Survei berjudul Penilaian Masyarakat terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis di 34 provinsi membeberkan fakta cukup mengejutkan. Pertama, sebanyak 81,9% responden lebih nyaman hidup dalam keturunan keluarga yang sama. Kedua, sebanyak 82,7% lebih nyaman hidup dalam lingkungan ras yang sama. Ketiga, sebanyak 83,1% lebih nyaman hidup dengan kelompok etnis yang sama.
Rentetan fakta itu menunjukkan tingkat segregasi sosial di masyarakat sangat berpeluang terjadi karena sikap yang masih terlalu nyaman dengan budaya yang sama. Masih relatif sulit untuk menerima keragaman atau kemajemukan.
Hal itu sejalan dengan data Komnas HAM yang mencatat sedikitnya ada 101 kasus diskriminasi ras dan etnis terjadi pada selama periode 2011-2018. Dalam kasus diskriminasi itu terjadi pada pelayanan publik baik pemerintah maupun swasta. Yang menarik, angka tertinggi dicatat pada 2016 dengan 38 kasus.
Dengan data tersebut menunjukkan nilai kebinekaan masih begitu tipis dalam diri warga Indonesia. Maka tidak salah jika asas kebinekaan perlu hidup dalam pendidikan tinggi. Bahkan, bagian penjelasan UU No 12 Tahun 2012 mempertegas kebinekaan dalam pendidikan tinggi sebagai penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan serta menghormati kemajemukan masyarakat Indonesia dalam negara kesatuan Republik Indonesia.
Dari sana muncul kekhawatiran. Apakah dosen asing itu mampu membawa nilai kebinekaan? Apakah rektor asing itu mampu menelurkan kebijakan yang berkarakter kebinekaan? Pertanyaan tersebut terasa berat untuk mampu dijawab. Karena realitasnya bangsa ini pun tidak seutuhnya mampu menjalankan konsep kebinekaan. Bagaimana pula dengan dosen dan rektor asing itu?
Pantas kiranya mengutip pendapat Budi Nugroho (2018) bahwa tindakan dan pikiran manusia merupakan produk dari serangkaian nilai yang diyakininya. Itu berarti rektor asing dan dosen asing ialah individu yang membawa nilai-nilai lokalnya. Nilai-nilai yang tumbuh dalam kebudayaannya yang nilai budayanya tidaklah sama dengan nilai-nilai bangsa Indonesia, terutama nilai kebinekaan.
Argumentasi itu bukan tanpa dalih kuat. Rektor asing dan dosen asing yang didorong sebagai mesin perubahan dalam pendidikan tinggi di Indonesia, pantas untuk diragukan mampu membawa nilai kebinekaan karena mereka lahir dalam lingkungan yang relatif tidak majemuk, seperti anak-anak Indonesia.
Pendidikan tinggi dan penguatan watak bangsa
Menukil pesan pada Pasal 3 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan, "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, ...".
Secara sederhana, karakter dan watak bangsa ini ialah menguatnya ideologi Pancasila. Mengimplementasikan nilai Pancasila dalam keseharian. Itu artinya pendidikan di kampus ialah bagian proses penguatan watak Pancasila dalam diri generasinya. Sejalan dengan itulah kehadiran rektor asing dengan membawa model pengelolaan pendidikan tinggi luar, bisa jadi merupakan benturan bagi lahirnya pribadi generasi Indonesia yang memiliki watak khasnya, yakni Pancasila.
Alasannya sangat sederhana, bahwa nilai Pancasila ialah identitas bangsa Indonesia yang idak dimiliki bangsa lain. Maka wajarlah sedikit pertanyaan, apakah nilai Pancasila itu juga dipahami rektor asing dan dosen asing?
Meski demikian, bukan berarti nada pesimistis terhadap kedatangan rektor asing dan dosen asing karena tidak bisa pula diingkari interaksi di era global membawa pengaruh baru bagi setiap bangsa. Globalisasi juga memaksa bangsa manapun untuk lebih berani terbuka, bekerja sama dan sebagainya. Hanya kendali penuh pemerintah terhadap manuver dan pola kebijakan rektor asing maupun dosen asing harus dikontrol sedemikian rupa. Semoga Indonesia akan lebih menjadi negara bermartabat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved