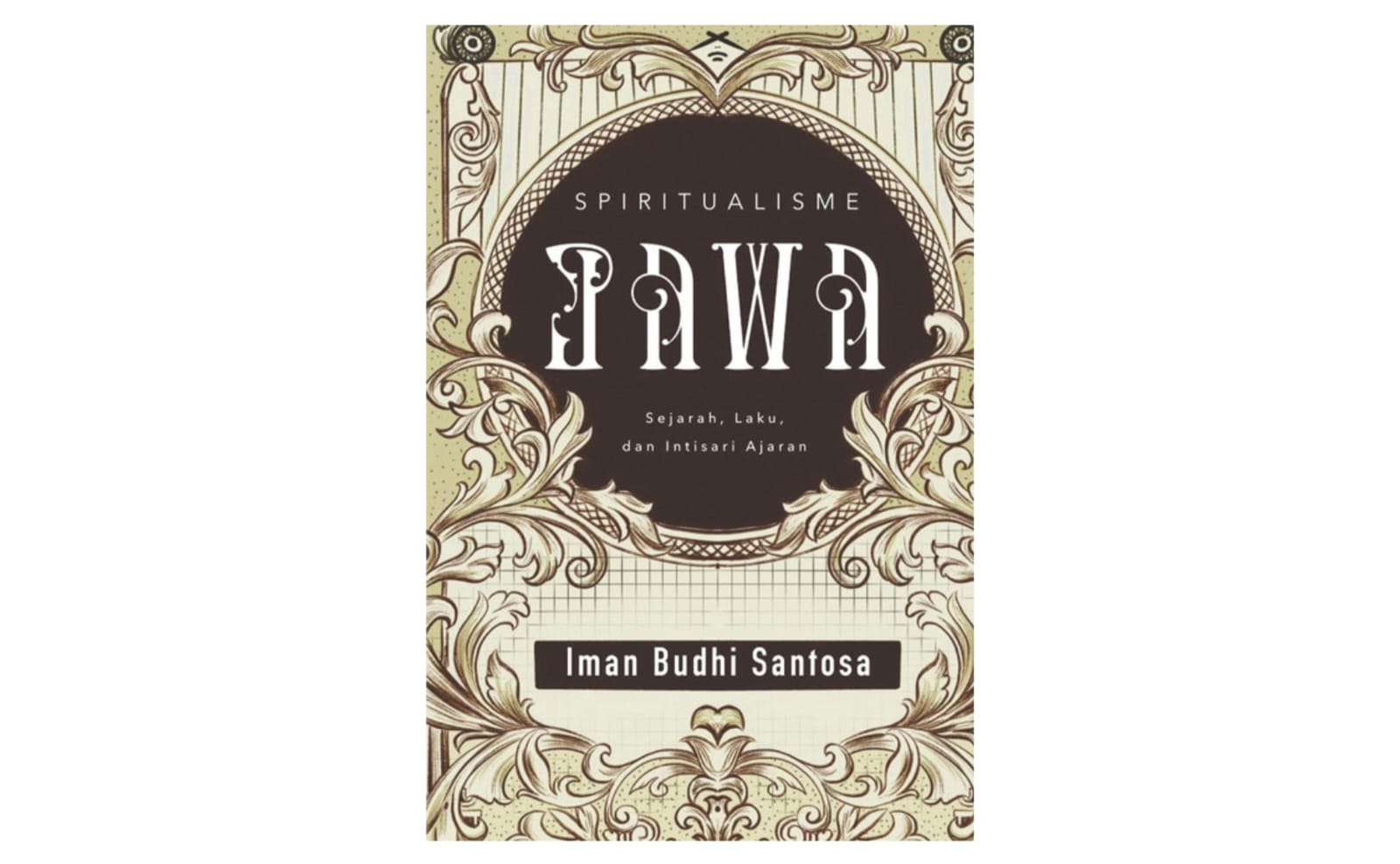Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
 Kumpulan Berita DPR RI
Kumpulan Berita DPR RI
SETIAP kebudayaan di Indonesia memiliki ciri khas dan makna dalam setiap unsurnya, tidak terkecuali kebudayaan Jawa. Salah satu yang identik dengan budaya masyarakat Jawa, utamanya yang berasal dari wilayah tengah dan timur di Pulau Jawa ialah kejawen.
Kejawen merupakan peleburan antara Islam dan kepercayaan dari budaya tradisional Jawa yang telah melekat sejak ratusan tahun di masyarakat Jawa. Layaknya setiap kepercayaan, kejawen juga memiliki banyak nilai dan ajaran kebaikan yang perlu diamalkan penganutnya.
Pada masyarakat Indonesia awam, pemahaman akan kejawen kerap tak utuh. Tidak jarang kejawen hanya dipahami sebagai aliran dan kegiatan yang berbau mistis, klenik, dan bersifat gaib.
Kesalahpahaman itu yang mungkin ingin diluruskan oleh penulis Iman Budhi Santosa melalui buku teranyarnya, Spiritualisme Jawa. Dalam buku ini, Iman, yang sebelumnya menulis Nasihat-Nasihat Hidup Orang Jawa, mencoba untuk menghadirkan secara lebih lengkap fakta-fakta tentang nilai, ajaran, hingga kepercayaan batin orang Jawa sejak masa Hindu-Buddha hingga masuknya Islam.
Terdapat empat bagian dalam buku ini yang mengangkat beragam tema, mulai kepercayaan, sejarah, hingga nasihat-nasihat hidup yang selama berabad-abad lamanya dipegang oleh masyarakat Jawa.
Bagian pertama buku membahas mengenai pandangan dan kepercayaan orang Jawa tentang keselamatan dalam hidup. Ajakan untuk selalu hidup dalam kebaikan demi mendapat keselamatan telah lama digaungkan melalui nasihat hingga peribahasa.
“Kehidupan orang Jawa boleh dikata penuh dengan angger-angger dan wewaler, aturan dan larangan, yang tujuan utamanya tiada lain ialah untuk mengatur perilaku individu dan masyarakat agar memperoleh, ketenteraman, dan keselamatan hidup dunia dan akhirat,” halaman 17.
Dalam bagian ini juga dibahas nilai-nilai dan ajaran yang ada di masyarakat Jawa tentang berbagai hal. Mulai tradisi saat terjadi kematian, ajaran untuk hidup bertetangga, adab mengadakan acara, hingga beberapa pandangan orang Jawa tentang hal-hal yang ada dalam kehidupan. Salah satunya terhadap alam.
“Dengan demikian jelas bahwa membangun keselarasan (harmoni) dengan alam lingkungan tempat tinggal ialah cara orang Jawa menemukan ketenteraman hidup seperti dinasihatkan oleh para leluhur di Jawa bahwa manusia harus pandai-pandai memayu hayuning bawana. Dengan berbuat baik kepada alam, alam pun akan memberikan berkah manfaatnya kepada manusia,” halaman 34.
Pada bagian kedua, penulis membahas dan memberikan pandangannya tentang penggolongan orang Jawa yang dicetuskan oleh Clifford Geertz. Ia mengklasifikasikan orang Jawa menjadi tiga golongan: santri, abangan, dan priayi.
“Seharusnya perlu dimunculkan pula golongan masyarakat Jawa yang bernama ‘rakyat jelata’ sebagai dikotomi priayi. Dalam kebudayaan Jawa, golongan ini disebut kawula alit (rakyat kecil/rakyat jelata), dan dalam dunia pewayangan lazim dinamai kaum pidak pedarakan (hina dina),” halaman 89.
Dihadirkan pula pembahasan dengan lebih detail mengenai sejarah penggolongan orang Jawa tersebut. Mulai masa jauh sebelum kemerdekaan atau sejak masih hidupnya kerajaan-kerajaan di Jawa hingga era modern saat ini.
Sebagai bagian yang khas dari kebudayaan Jawa, penulis juga tak lupa menyertakan nilai-nilai dan ajaran yang tertuang dalam beberapa serat. Di antaranya Serat Waraiswara, Serat Sasanasunu, Serat Bratasunu, Serat Wedhatama, dan Serat Nitisruti.
Penjabaran isi serat dan nilai-nilai ajaran luhur yang terkandung di dalamnya dihadirkan penulis dalam bahasa yang sederhana, juga dihadirkan contoh atau cuplikan isi serat yang membahas mengenai ajaran-ajaran tersebut.
Tak lupa juga disertakan info mengenai sejarah dan latar belakang setiap serat tersebut. Dengan begitu, pembaca juga sekaligus akan mendapatkan informasi dan pengetahuan mengenai serat-serat yang ada di Jawa serta para penulis atau penemunya.
Dari serat-serat itu dimunculkan beberapa nilai tentang perilaku yang hingga saat ini masih banyak menjadi pedoman hidup orang Jawa. Di antaranya tentang keseimbangan dunia dan akhirat, memelihara akal, adab mencari nafkah, berpenampilan, hingga tata cara mengeluarkan pendapat.
Beberapa peribahasa dan petikan penting yang termuat di serat-serat tersebut juga turut ditampilkan. Salah satunya dari Serat Wedhatama.
“Ngelmu iku kalakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosani, setya budaya pengkese dur angkara. (Ilmu itu dijalankan dengan perbuatan, dimulai dengan kemauan. Kemauan adalah penguat, budi setia penghancur kemurkaan),” halaman 127.
Bagi penggemar peribahasa, di bagian ini penulis juga menghadirkan puluhan peribahasa Jawa yang dirangkum dari berbagai serat-serta yang diwariskan melalui tradisi lisan orang-orang Jawa. Peribahasa-peribahasa tersebut ditampilkan berkelompok sesuai dengan tema nasihat yang terkandung.
Tak hanya itu, juga terdapat perjelasan lebih detail mengenai sejarah, pemaknaan, dan jenis-jenis peribahasa dalam ranah bahasa dan susatra Jawa. Disebutkan bahwa peribahasa atau yang dalam bahasa Jawa disebut unen-unen, terbagi menjadi enam kelompok, yakni paribasan, bebasan, saloka, pepindhan, sanepa, dan isbat.
Masing-masing memiliki ciri khas dan tema nasihat yang berbeda-beda. Semuanya dijelaskan dengan singkat, tetapi padat dan informatif oleh penulis.
Pada bagian ketiga, penulis membahas mengenai akar spiritualisme Jawa. Termasuk faktor-faktor yang membentuk kejawen hingga saat ini. Di antaranya pandangan hidup yang terus tumbuh dan berkembang sejak masih dipegangnya kepercayaan lama animisme dan dinamisme, hingga kemudian masuknya agama-agama di Indonesia. Tak lupa juga pengaruh pergerakan ideologi-ideologi lain, sosial, budaya, dan dinamika kehidupan lainnya.
“Karena itulah, siapa pun yang pernah berkenalan, berkomunitas, atau tinggal cukup lama bersama orang Jawa sehingga tahu benar mengenai ‘lambe atine’, umumnya akan memberikan semacam pangalembana (sanjungan) dengan jujur ketika menilai karakter mereka, bahwa orang Jawa itu religius, ramah, terbuka, sopan, lentur, mudah bersahabat, dan senantiasa menghormati orang lain,” halaman 188.
Rohani
Di bagian ketiga ini penulis menghadirkan informasi lebih lengkap mengenai perjalanan masuknya agama-agama di Jawa. Mulai masa kepercayaan sebelum Hindu-Buddha, masa Hindu-Buddha, hingga masuknya Islam sekitar abad XIII di tanah Jawa.
Penulis mengungkapkan bahwa kepercayaan lama animisme dan dinamisme, serta agama Hindu, Buddha, dan Islam merupakan yang paling memiliki pengaruh kuat di kehidupan orang Jawa. Sementara itu, Kristen, Katolik, dan Konghucu, kurang memberikan pengaruh signifikan terhadap adat tradisi Jawa karena pemeluknya relatif kecil.
Pada bagian keempat atau terakhir dalam buku, penulis membahas mengenai hubungan kepercayaan lokal dengan agama-agama yang berkembang di Jawa. Hubungan yang akhirnya memunculkan pandangan rohani atau kebatinan orang Jawa yang disebut kejawen.
Hubungan antara hal-hal tersebut yang kemudian menjadi pedoman hidup orang Jawa hingga saat ini. Sebagai kesimpulan, penulis membahas mengenai kejawen sebagai spiritualisme yang secara tersirat dan tersurat lebih mendekati filsafat-filsafat khas Jawa. Dalam kejawen, terdapat berbagai ajaran filsafat dengan sumber yang berbeda-beda atau tidak bersifat homogen.
Meski membahas hal-hal yang tidak sederhana, pemaparan yang disajikan dalam buku ini secara umum mudah dicerna. Penulis yang telah tutup usia pada Desember 2020, menghadirkan informasi bernuansa sejarah dan filsafat dengan gaya bahasa tulis populer.
Melalui berbagai pemaparan, contoh, dan pendapatnya dalam buku ini, Iman Budhi Santosa cukup berhasil menyampaikan informasi yang utuh tentang spiritualisme Jawa, tentang kejawen dan berbagai nilai, unsur pembentuk, dan pemaknaan di dalamnya, bahwa kejawen ialah bagian dari filsafat hidup orang Jawa yang tak melulu berisi soal klenik, mistis, dan hal-hal gaib.
“Dengan filsafat kejawennya itu, orang Jawa justru telah berhasil memayu hayuning bawana sehingga jutaan orang merasa aman, nyaman, dan tenteram hidup di Jawa selama ini,” halaman 6. (M-2)
_____________________________________________________________________
Judul Spiritualisme Jawa
Penulis Iman Budhi Santosa
Penerbit Diva Press (Desember 2021)
ISBN: 978-623-293-583-9
Kemenhub kembali mengadakan program mudik gratis untuk Lebaran 2026. Pemerintah menyiapkan 78 ribu kursi untuk kapal laut dan kereta api. Sedangkan untuk angkutan darat, disediakan 401 unit bu
CENS merupakan pergerakan massa udara dingin dari wilayah Tiongkok Selatan yang mampu melintasi garis ekuator hingga mencapai wilayah Indonesia.
Kondisi ini dipicu oleh penguatan Monsun Asia dan adanya sistem tekanan rendah di selatan Nusa Tenggara Barat yang membentuk pola konvergensi atau pertemuan angin.
Kondisi ini dipicu oleh aktivitas Bibit Siklon Tropis 91W dan penguatan Monsun Asia yang meningkatkan potensi hujan lebat disertai angin kencang di jalur Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara.
Berikut prakiraan cuaca Senin 12 Januari 2026 untuk kota-kota besar di Indonesia dikutip dari BMKG
Peta sebaran bencana sepanjang 2025 menunjukkan Pulau Jawa dan Sumatra masih menjadi wilayah dengan jumlah kejadian bencana tertinggi di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved