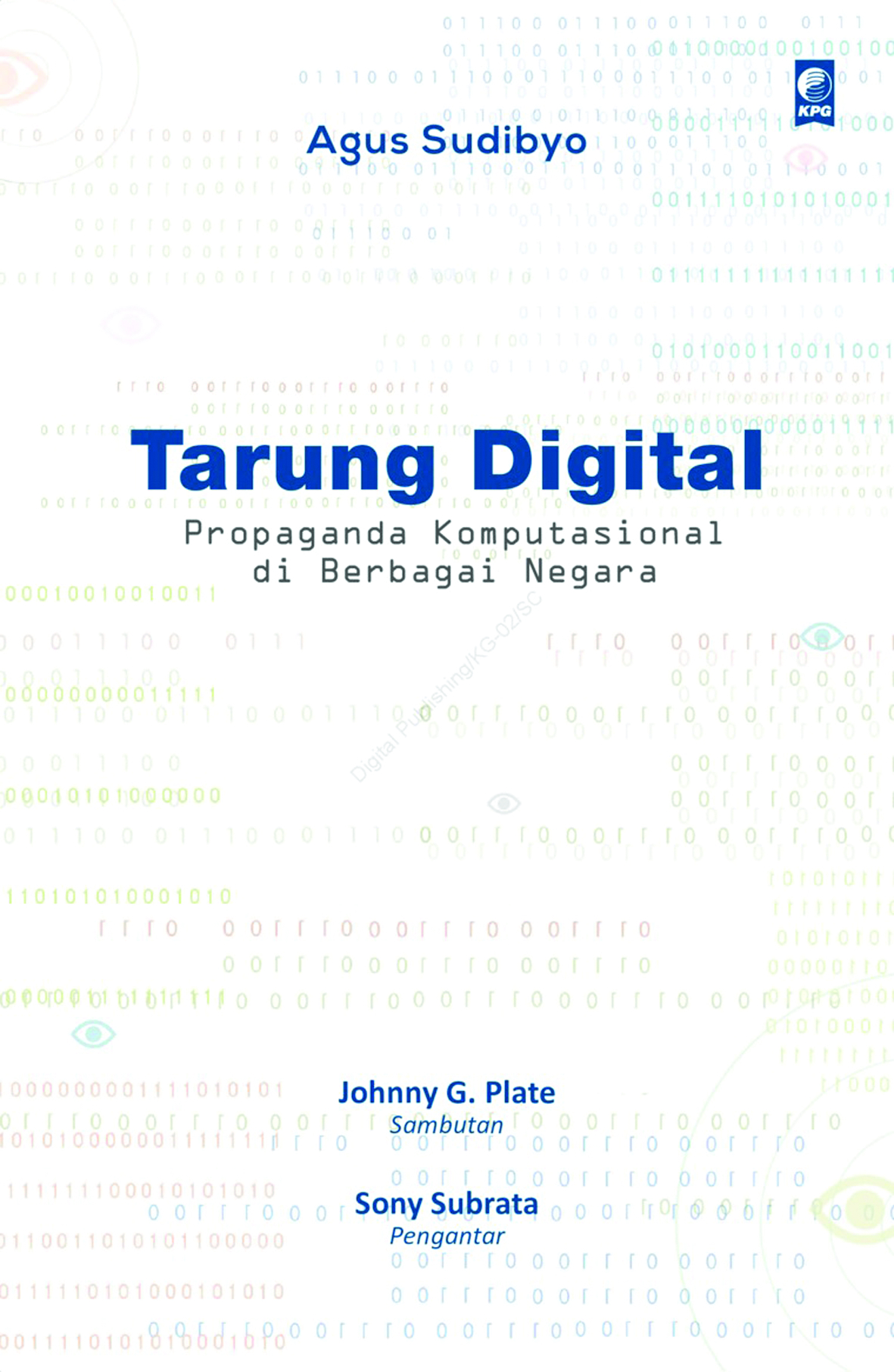Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
 Kumpulan Berita DPR RI
Kumpulan Berita DPR RI
SEJAK internet ditemukan pada akhir medio 1960-an, beragam platform (komunikasi) baru pun terus bermunculan, mulai mesin pencarian, kanal berita, hingga media sosial yang menawarkan akses informasi tak terbatas serta cara-cara baru dalam berkomunikasi yang tidak pernah ada sebelumnya. Namun, masalah baru kemudian muncul ketika aneka platform itu bersinggungan dengan diskursus politik.
Ketika pranata-pranata digital tersebut mulai dimanfaatkan sebagai sarana propaganda politik, ruang-ruang komunikasi baru yang awalnya relatif netral mulai terpapar oleh pola komunikasi yang tidak sehat. Propaganda politik yang kemudian menyublim ke bentuk 'komputasional' (berbasis algoritma) itu biasanya akan diikuti dengan kemunculan informasi-informasi palsu yang memiliki tujuan manipulatif serta praktik-praktik ujaran kebencian yang merugikan banyak pihak.
Dalam perkembangannya, propaganda komputasional itu menjelma menjadi sebuah permasalahan global yang tak hanya menggembosi demokrasi, tetapi juga kerap menjadi penyebab utama timbulnya suatu perpecahan sosial. Fenomena itu tak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai belahan dunia.
Buku bertajuk Tarung Digital: Propaganda Komputasional di Berbagai Negara karya Agus Sudibyo ini hadir untuk menjelaskan kekarut-marutan dari wacana internet of things (IoT) yang sering kali mentok akibat propaganda komputasional. Buku ini menjelaskan latar belakang, lingkup persoalan, hingga dampak fenomena paling mutakhir yang terjadi dalam perkara digitalisasi politik kita hari ini.
Buku ini diawali dengan sebuah narasi tentang suksesi kekuasaan di Amerika Serikat yang diintervensi intelijen Rusia lewat teknologi komputasi yang luar biasa. Sarananya ialah media sosial yang familier kita gunakan sehari-hari; Facebook, Youtube, Twitter, dan Instagram. Di situ, mereka menyebarkan propaganda politik yang tujuannya memecah belah pemilih dalam Pemilu AS 2016, Donald Trump vs Hilary Clinton.
Pada awalnya, tak ada yang menduga bahwa media sosial dapat digunakan sebagai sarana manuver politik yang merusak itu, hingga akhirnya Amerika Serikat menjadi pihak (korban) yang paling dirugikan dari penyalahgunaan media sosial itu sendiri.
'Tak pelak lagi, kegeraman dan kepanikan pun terjadi di mana-mana. Tak hanya pemerintah AS yang merasa kecolongan, tetapi pemerintah Inggris, Uni Eropa, Israel, India, dan lain-lain. Muncul keyakinan bahwa praktik penyalahgunaan data pengguna media sosial untuk memobilisasi suara masyarakat juga terjadi di negara-negara tersebut' (halaman 18).
Namun, belakangan propaganda komputasional itu dianggap sebagai sebuah kelaziman, terutama pada momen-momen tertentu yang berhubungan dengan peralihan kekuasaan. Publik pun selalu terlambat menyadari, bahkan sering kali hanya jadi korban dari manuver-manuver tak bertanggung jawab yang dilancarkan para aktor politik lewat propaganda komputasi tersebut.
'Platform media sosial juga mengemuka sebagai instrumen mobilisasi politik berlandaskan prasangka, kepalsuan, dan kebohongan. Media sosial juga membawa politik ke arah "dehumanisasi"... Manipulasi pada level interaksi sosial kemudian melahirkan manipulasi pada level lain: pemahaman, kesadaran, dan pilihan politik masyarakat. Ketika interaksi sosial semakin terpola untuk dijalankan secara komputasional, aras komunikasi politik pun berada dalam kendali para the invisible hand' (halaman 30).
Bot politik
Dalam kerangka komunikasi politik, propaganda komputasional dapat dijelaskan sebagai sebuah proses agenda setting berbasis algoritma terkurasi, yang secara sengaja menyebarkan informasi-informasi menyesatkan dengan memanfaatkan data perilaku pengguna internet. Tujuannya membentuk suatu perilaku politik tertentu. Praktik manipulasi opini publik secara otomatis akan semakin membesar lewat proses pembelajaran mesin (machine learning) yang menyebarkan informasi-informasi palsu tersebut ke jejaring media sosial, bahkan kadang dapat merembet ke media-media konvensional yang konon katanya merupakan pilar penopang demokrasi.
Salah satu fitur kecerdasan buatan hasil dari proses pembelajaran mesin yang banyak dirujuk dalam propaganda komputasional itu ialah sebuah perangkat lunak yang dikenal dengan istilah 'bot'. Dalam propaganda kokmputasional, bot berfungsi untuk membentuk opini publik lewat jawaban-jawaban berbasis mesin yang sering kali ia layangkan untuk meramaikan suatu percakapan daring.
Namun, pada praktiknya penggunaan bot untuk mengangkat suatu isu politik biasanya dikombinasikan dengan peran operator manusia yang disebut 'troll'. Setelah bot berhasil meramaikan percakapan, troll akan bergerak untuk membentuk dan mengarahkan opini publik ke suatu argumen tertentu yang (diharapkan) mampu memengaruhi preferensi politik seseorang.
'Diskusi tentang bot politik lazim merujuk pada akun-akun media sosial terotomatisasi yang tidak hanya berfungsi untuk melakukan interaksi semu dengan para pengguna media sosial, tetapi juga bertindak sebagai agen propaganda untuk mewujudkan misi politik partikular. Bot politik dalam perkembangannya identik dengan aktivitas ilegal pada aras politik elektoral seperti pemalsuan akun, penyebaran ujaran kebencian atau berita bohong, maupun praktik doxing atau phishing' (halaman 73).
Selain membelejeti modus kerja propaganda komputasional, penulis memberikan beberapa contoh kasus penggunaan propaganda komputasional itu di berbagai negara di dunia. Penulis juga menggarisbawahi perbedaan pola penggunaan propaganda komputasional di negara yang berhaluan otoriter dan demokratis, seperti yang ia kemukakan dalam ringkasan praktik propaganda komputasional di sembilan negara: Brasil, Kanada, Tiongkok, Ukraina, Jerman, Polandia, Taiwan, Rusia, dan Amerika Serikat.
'...pemerintah otoriter mengerahkan propaganda komputasional dengan menyasar warga mereka sendiri dan penduduk negara lain... Sementara di negara demokrasi, akun-akun media sosial palsu dan terotomatisasi lebih banyak dirancang dan dijalankan para pengguna individu. Kandidat politik, juru kampanye, dan pelobi menyewa jaringan akun media sosial yang secara khusus diciptakan untuk menggarap momentum pemilu' (halaman 45).
Untuk pengalaman Indonesia, penulis mengutip hasil amatan dari Drone Emprit dan hasil penelitian bertajuk Computational Propaganda Research Project yang dikeluarkan Oxford Internet Institute untuk menjelaskan fenomena propaganda komputasional yang terjadi di Indonesia selama gelaran Pilpres 2019 (halaman 217).
Dengan terang benderang, buku ini berhasil menjelaskan fenomena pergeseran arena pertarungan politik di era digital, ketika bahasa algoritma begitu berkuasa. Propaganda politik yang dulunya begitu telanjang (dan kadang membosankan) lantaran masih dilakukan dengan cara konvensional kini sebagian besar telah menyublim ke bentuk paling mutakhirnya, merangsek ke pori-pori kesadaran kita lewat suplai informasi yang kita konsumsi setiap hari di media sosial.
Walau belum tentu selamat, membaca buku Tarung Digital dapat membuat kita lebih awas terhadap serangan propaganda di pesta-pesta politik mendatang. Syukur-syukur, buku ini membantu kita mengamankan akal sehat demi pilihan-pilihan atas nama kesadaran. (M-2)
Penulis
Agus Sudibyo
Judul
Tarung Digital
Propaganda Komputasional di Berbagai Negara
Penerbit
Kepustakaan Populer Gramedia
Maret 2021
xxiv + 368 halaman
ISBN 978-602-481-552-3
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved