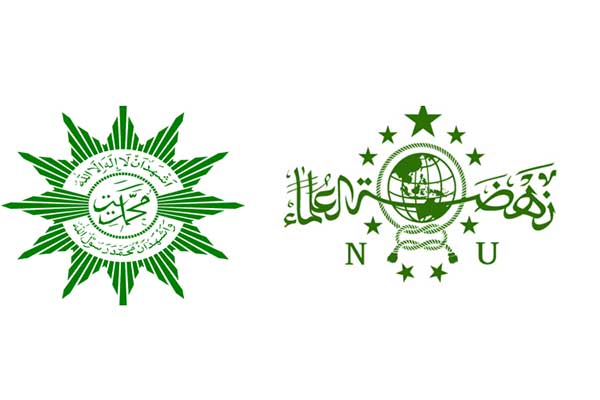Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
 Kumpulan Berita DPR RI
Kumpulan Berita DPR RI
PADA akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, terjadi perdebatan metodologi (methodenstrait) di Jerman. Perdebatan ini sangat sengit untuk menentukan apakah ilmu ekonomi merupakan ilmu dengan logika nomologis yang berciri ekonometri atau logika ideografis yang menekankan wawasan sosial-budaya.
Di tengah persitegangan akademik, Max Weber, sebagai empu sosiologi, menyerukan sebuah paradigma yang bertitik temu. Weber menawarkan spirit 'to bring the methode natural science and humanities under one roof' sebagai langkah strategis yang memadukan konsep eklaeren dan konsep verstehen dengan harapan, melalui pemaduan eklaeren dan verstehen, ilmuwan sosial tidak lagi terjebak dalam cara positivistik dalam melihat realitas sosial.
Warisan Weber ini memengaruhi banyak sosiolog yang hidup di daratan Eropa, yang di antaranya Juergen Habermas. Habermas melakukan rekonstruksi metodologis dengan cara to go beyond neo-Kantian epistemology. Melalui buku Zur Logic de Sozialwissenschaften yang dipublikasikan 1970-an, Habermas mengajak berbagai pihak agar bisa menjalin ilmu alam (naturwissenchaften), dan humaniora (geisteswissenschaften) secara berdampingan.
Spirit semipermeabel
Dalam konteks kekinian, ajakan titik temu dan sinergi yang disampaikan sang empu sosiologi tersebut perlu disadari pula oleh para pegiat sosiologi selanjutnya. Terlebih, pegiat sosiologi yang menjadi anutan publik seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, dengan figur KH Yahya Chalil Staquf (Gus Yahya) dan Prof Haedar Nashir merupakan pembelajar sosiologi jebolan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Selama belajar sosiologi, keduanya tentu sudah dibekali banyak konsep dan teori bagaimana memahami masyarakat dan merespons setiap perubahan sosial dengan baik. Karena itu, sangat diharapkan agar keduanya mampu menjadikan NU dan Muhammadiyah sebagai tanggung jawab sosial yang menginspirasi para pengikut dan berbagai lapisan masyarakat lainnya.
Setidaknya, spirit semipermeable, yaitu kesediaan dua unsur yang saling menembus, saling menyapa, dan bersinergi untuk menghasilkan sikap toleransi dan koeksistensi harus dibudidayakan sebagai ekosistem organisatorisnya. Sebagaimana jamak diketahui, keberadaan NU dan Muhammadiyah sering kali mengalami persitegangan ketika berhadapan dengan soal ubudiyah atau amaliyah.
Ungkapan satire 'kalau orang NU ke masjid, sandalnya yang hilang dan kalau orang Muhammadiyah ke masjid, qunutnya yang hilang' seolah menjadi cerminan konflik horizontal yang berkepanjangan. Mirisnya lagi, ungkapan itu semakin terafirmasi saat paradigma ubudiyah Muhammadiyah yang dilingkupi label takhayul, bidah, dan khurafat masih lestari.
Demikian pula, paradigma ubudiyah NU yang sangat menonjolkan unsur fadilah (keutamaan) dalam beribadah sehingga sebagian pengikut mereka memersepsikan fadilah tersebut sebagai hukum yang prinsipiel (ushuliyah). Dampaknya, dalam aspek ubudiyah, NU dan Muhammadiyah kerap kali berada di persimpangan, yang keduanya saling 'mendiskreditkan' karakteristik ideologi mereka.
Potret konfliktual tersebut seolah meneguhkan tradisi Kantian yang sebenarnya sudah lama 'dikubur' para empu sosiologi klasik seperti Weber dan empu sosiologi modern seperti Habermas. Sejatinya, potret buram ini harus diatasi dua figur pegiat sosiologi, yang kini sudah berkhidmat di pucuk pimpinan NU dan Muhammadiyah.
Oleh karena itu, untuk menumbuhkan spirit semipermeable di lingkungan NU dan Muhammadiyah, Gus Yahya dan Prof Haedar perlu merumuskan sosiologi terapan yang bisa mendudukkan platform organisasi NU dan Muhammadiyah yang saling menembus, merembes, dan saling menyapa dalam menyikapi praktik ubudiyah.
Belajar pada pendiri
Secara historis, spirit semipermeable sebenarnya sudah ditunjukkan para pendiri mereka. KH Hasyim Asy’ari sebagai pendiri NU dan KH Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah saling menggunakan kearifan dan kesahajaan dalam menyikapi setiap perbedaan ubudiyah. Selain itu, secara paradigmatik, di samping menggunakan khazanah keislaman, dua sosok pendiri itu sebenarnya menggunakan ilmu sosiologi pula dalam mentransformasi pendekatan dan metode beribadah kepada warga mereka.
Sebagai pembelajar agama, yang sama-sama berguru pada Kiai Shaleh Darat di Semarang dan keduanya sama-sama berguru pula kepada Syekh Khatib al-Minangkabawi dan Syekh Nawawi al-Bantani di Mekah, mereka saling mengamalkan cara ibadah yang diyakini keduanya. Selain itu, meskipun kedua figur ini memiliki jalur pergerakan yang berbeda, keduanya sama-sama mengabdikan diri untuk kemaslahatan agama dan bangsa dan tegaknya persatuan.
Dalam kaitan ini, sikap ketersalingan, titik temu, dan corak interaksi yang dicontohkan dua pendiri NU dan Muhammadiyah menjadi tapak historis dan legasi, yang perlu dilestarikan Gus Yahya dan Prof Haedar agar dua organisasi besar ini menjadi penjaga ukhuwah islamiyah, ukhuwah basyariyah, dan ukhuwah wathaniyah, yang bertanggung jawab sosial dan bermanfaat bagi peradaban dunia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved