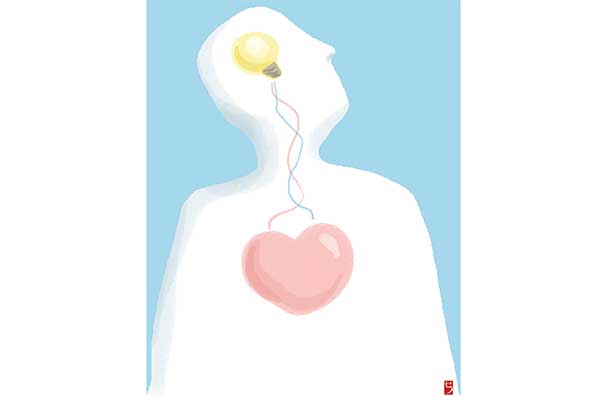Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
 Kumpulan Berita DPR RI
Kumpulan Berita DPR RI
'OTAK Habibie' ialah frasa yang hidup di Indonesia sejak paruh kedua 1970-an, yakni setelah kepulangan Bacharuddin Jusuf Habibie (1936-2019) dari perantauannya di Jerman. Dalam masa pendidikan dan kerja selama dua dasawarsa di Eropa, Habibie menjadi saintis-inventor yang berpengaruh di dunia, terutama dalam industri kedirgantaraan.
Di Tanah Air, Habibie tak kalah fenomenal. Beliau membangun industri kedirgantaraan Indonesia dan langganan menjadi orang nomor satu di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi serta terakhir menjadi Wakil Presiden dan kemudian Presiden Republik Indonesia. Dalam dunia pendidikan Indonesia, fenomena 'otak Habibie' mewujud dalam upaya-upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta kepemilikan iman dan takwa (imtak). Bahkan, kedua konsep itu kemudian diadopsi dalam Pasal 31 ayat 3 dan 5 UUD 1945 hasil amendemen.
Jika diperhatikan penjelasan Pasal 31 tersebut dan UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta berbagai regulasi turunannya, tujuan yang hendak dicapai lebih tepatnya ialah terjadinya perkawinan antara iptek dan imtak dalam diri murid-murid. Output pendidikan, oleh karena itu, hendaklah cerdas dan terampil di atas dasar spiritualitas. Namun, adopsi warisan Habibie ini dalam dunia pendidikan menumbuhkan paling kurang dua masalah yang tak mudah diselesaikan. Utamanya terkait dengan pengerasan simbolisasi keberagamaan dan kedua terkait dengan penilaian pendidikan.
Simbolisasi keberagamaan
Salah satu cara menjelaskan hal ini, menurut hemat penulis, ialah dengan mengatakan bahwa Habibie terlalu cerdas dan maju sehingga tak mudah dipahami dan diikuti para pengambil kebijakan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Dikatakan demikian, karena beliau merupakan seorang yang logis-rasional serta penghayat dan pengamal demokrasi sejati. Pendidikan dan pengalaman hidup di Eropa serta bacaan yang dalam tentang agama, membuat beliau berjarak dari realitas keberagamaan masyarakat Indonesia.
Contoh pertama ialah terkait dengan cita-cita terjadinya perkawinan iptek dan imtak dalam diri murid atau mahasiswa. Karena sudah menjadi amanah konstitusional, secara nasional cita-cita ini dikurikulumkan, dibuatkan prosedur operasionalnya dan disosialisasikan secara masif. Sampai saat ini, kedua gagasan tersebut menghiasi dinding-dinding sekolah, diulang-ulang dalam berbagai seremoni, diterangkan dalam berbagai buku teks dan diujikan.
Namun, di sinilah letak pangkal masalahnya, yakni formalisasi gagasan yang dipahami dan dikembangkan tanpa kontekstualisasi. Pertama, formalisasi perkawinan iptek dan imtak dalam dunia pendidikan tidak memperhatikan aspek dialektis atau pergumulan di antara keduanya dalam diri murid seperti yang terjadi pada Habibie. Para pembuat kebijakan pendidikan terjebak dalam logika formalisasi sebagai penyeragaman atau standardisasi yang mengabaikan keunikan atau keberagaman manusia. Alhasil, murid-murid cenderung mengalami pembelajaran agama sebagai proses menghafal simbol dan teks dan menyakralkannya.
Kedua, formalisasi gagasan perkawinan iptek dan imtak dalam diri murid cenderung berujung pada agamaisasi ilmu pengetahuan. Bukannya fokus pada proses belajar berdasar pada fakta-fakta alamiah, ekonomi atau sosiokultural masyarakat di mana murid-murid hidup, murid-murid disuguhkan berbagai materi pelajaran yang dipaksakan terlihat berkorelasi dengan nilai-nilai agama. Hal itu tidak saja membingungkan dan membodohkan, tetapi juga memiskinkan pengetahuan dan penghargaan murid akan keunikan dan kearifan lokal serta keberagaman.
Oleh karena kedua sebab di atas, alih-alih terjadinya perkawinan antara iptek dan imtak dalam diri murid, yang terjadi ialah bertumbuh dan berkembangnya simbolisasi keberagamaan. Seiring waktu, pengulangan dan pembiasaan yang diperkuat dengan berbagai stimulasi eksternal seperti konflik horizontal yang mengandung unsur agama menyebabkan pengerasan identitas yang detrimental.
Contoh berikutnya ialah terkait dengan demokrasi. Dalam satu sesi diskusi dengan beberapa tokoh agama nasional di salah satu televisi swasta, yakni ketika politik identitas makin mengeras di awal April 2019, Habibie berbicara tentang human vicegerency atau manusia sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Dalam pemahamannya, yang rasional dan humanis, manusia sudah diberi Tuhan hak sekaligus kapasitas untuk mengelola urusan keduniaan seperti politik sehingga tidak pada tempatnya jika ada yang mengklaim bahwa diri atau kelompoknya saja yang menjadi pembela panji-panji Tuhan.
Mengikuti gagasan tentang human vicegerency ini, demokrasi ialah penemuan manusia dengan menggunakan kapasitas yang sudah dianugerahkan Tuhan. Namun, tidak semua orang mampu berdemokrasi. Orang-orang yang lemah, alpa atau malas akan cenderung mengeksploitasi identitas keagamaan dalam politik sebagai jalan pintas. Contoh paling dekat tentulah bagaimana agama menjadi komoditas yang laris pada Pemilu 2019.
Habibie sendiri sempat dituding terlibat dalam menggalang massa kelas menengah Islam, yakni ketika mendirikan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada 1990. Dinyatakan bertujuan memberantas kemiskinan dan mengembangkan pendidikan, lembaga ini menjadi pemicu terlahirnya lembaga-lembaga kaum intelektual di lingkungan agama lainnya.
Hemat penulis, terlepas dari konteks politik di dasawarsa terakhir Presiden Soeharto tersebut, tindakan Habibie mendirikan ICMI tidaklah keluar dari koridor demokrasi. Itu karena kita tahu demokrasi membebaskan siapa pun atau kelompok mana pun untuk mengorganisasikan diri, seperti dijamin UUD 1945. Bahkan, di negara-negara maju di Eropa, sebagai contoh, kelompok ekstrem seperti Hizbut Tahrir, yang kini dilarang di Indonesia, boleh hidup.
Hanya, ini menjadi salah satu catatan penting di sini, masyarakat Indonesia belum terdidik dan terbiasa untuk berdemokrasi seperti itu. Alhasil, inovasi Habibie, yang tidak salah secara konsep ternyata belumlah operasional dalam hal konteks.
Ketakterukuran imtak
Formalisasi perkawinan iptek dan imtak selanjutnya menjadi biang masalah dalam penilaian pendidikan dan berimplikasi pada makna keberagamaan di lingkungan pendidikan. Itu karena ketika penguasaan ilmu pengetahuan (selanjutnya kita sebut saja 'sains') dan teknologi bisa dinyatakan bersifat tangible dan oleh karena itu bisa diukur (measurable), tidaklah demikian halnya keberimanan dan kebertakwaan. Spiritualitas atau religiositas hakikinya ialah perkara batin.
Bagaimanakah kita bisa mengukur kadar iman dan takwa seorang murid? Apakah alat ukur yang bisa dipercaya? Jika caranya ialah dengan pengamatan perilaku, bagaimana dengan subjektivitas guru dan kemungkinan keberpura-puraan murid demi nilai yang tinggi?
Jika demikian halnya, perkara pembelajaran untuk membangun imtak harus dikembalikan ke asalnya, yakni sebagai pengembangan entitas dalam ranah privat yang tak perlu diukur-ukur orang lain selain diri si murid. Jika bercermin pada pengalaman hidup Habibie, keberagamaan harus dilihat sebagai proses yang terus-menerus secara unik, personal, dan kaya. Tugas lembaga pendidikan hanyalah memfasilitasi dengan lingkungan belajar yang positif serta sumber belajar yang kaya.
Dengan cara ini, semoga, kita bisa melihat dan menggunakan warisan Habibie secara lebih tepat. Selamat jalan, Pak Habibie.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved