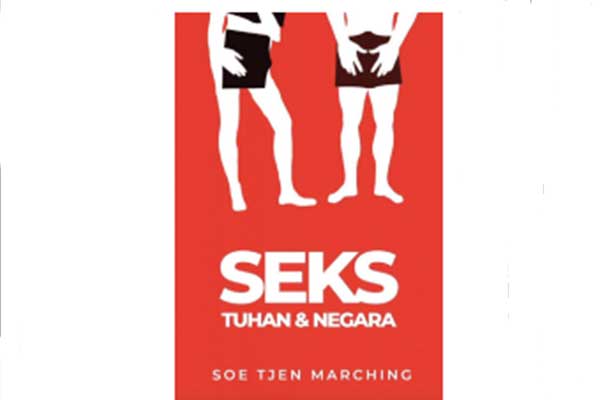Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
 Kumpulan Berita DPR RI
Kumpulan Berita DPR RI
BARANGKALI tidak sedikit yang sepaham dengan artikel berjudul ‘Kemerdekaan Indonesia: Untuk Siapa?’, yang termaktub dalam buku Seks, Tuhan, dan Negara karya Soe Tjen Marching.
Sepertinya artikel itu ditulis kala Indonesia berulang tahun ke-70. Ada beberapa hal diketengahkan. Salah satu yang paling kentara ialah soalan penindasan, utamanya tragedi di Aceh, Papua, dan Timor Leste yang terjadi pada 1965.
‘Lalu apa artinya perayaan kemerdekaan bila korban dari berbagai kekerasan massa masih ditindas? Bukankah ini justru mengingkari sumpah dari UUD 1945 itu sendiri?’ (hlm 152).
Penulis memberi refl eksi terkait perayaan kemerdekaan dengan kutipan dari Ki Hadjar Dewantara. Kala itu, Ki Hadjar mengecam rencana pemerintah kolonial Belanda yang hendak merayakan kemerdekaan di beberapa wilayah jajahan.
Bukankah hal itu ironis? Perayaan kemerdekaan di tengah jutaan warga negara yang terampas kemerdekaannya. Artikel ‘Kemerdekaan Indonesia: Untuk Siapa?’ bukan satusatunya yang mengetengahkan ironi dalam buku terbitan Global Indo Kreatif ini.
Bahkan, ironi telah tampak dalam sinopsis dan pengantar di bagian awal buku, ketika dituliskan, ‘Seks adalah hal yang masih sering ditabukan, namun negara dan Tuhan gemar sekali mengaturnya, terutama terhadap wanita. Perempuanlah yang sering kali menjadi sasaran berbagai per aturan tentang pakaian dan perilaku seksual’ (hlm 1-2). Sampai di situ pembaca barangkali sudah cukup mendapat pemahaman terkait ide utama dalam buku setebal 265 halaman ini.
Namun, ternyata lebih dari sekadar tiga tema seks, Tuhan, dan negara yang saling bertaut. Banyak bahasan yang diturunkan dari salah satunya. Buku karya dosen School of Orien tal and African Studies (SOAS) University of London ini memang merupakan antologi artikel yang
ditulis dalam rentang 2001-2020.
Alhasil, di dalamnya muncul banyak tema yang mungkin bisa jadi tidak berkait antara satu dan yang lain. Tiap artikel punya pokok bahasan dan tekanan tersendiri. Namun, secara garis besar, tiap artikel tetap berada dalam tematema besar yang menjadi judul buku.
Untuk mempermudah pembacaan, buku ini terbagi menjadi tiga bagian, yakni Seks dan Gender; Negara dan Kekuasaan; serta Tuhan, Dogma, Agama. Ketiganya menjadi pernyataan penulis terkait kondisi kontemporer. Ia melawan dogma dan propaganda dengan kata-kata.
Menarik untuk memperhatikan penyataan penulis; bila akal budi sudah dipenuhi oleh dogma, bila cara berpikir sudah dibentuk oleh penguasa, akan dengan mudah dikendalikan untuk memenuhi tujuan tertentu. ‘Karena itu, dengan kata-kata pula, saya mencoba melawan berbagai propaganda dan dogma’ (hlm 3).
Artikel ‘Kemerdekaan Indonesia: Untuk Siapa?’ adalah bagian dari Negara dan Kekuasaan. Selain itu, masih ada 27 artikel lain. Salah satunya menyorot tentang kewarganegaraan yang dimaknai secara sempit oleh beberapa golongan. Bahwa orang Indonesia adalah pribumi, bukan Cina.
Dalam Ahok & Cina, penulis membahas persoalan identitas anak bangsa yang seolah dipecah hanya menjadi dua, yakni pribumi dan Cina. Ia menggunakan kejadian yang menimpa mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai pintu masuk.
Berkalikali Ahok menekankan bahwa dia adalah orang Indonesia. Seakan dia harus berjuang hanya untuk mendapat pengakuan tersebut. Padahal berdasarkan UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, konsep Indonesia asli adalah orang yang menjadi warga negara sejak lahir dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri.
Nyatanya, pandangan miring itu tidak hanya menimpa Ahok, penulis pun menghadapi hal yang sama. Ketika di luar negeri ia dikenal sebagai orang Indonesia, justru di kampung halaman, ia disebut Cina.
‘Namun, ketika saya pulang ke tempat saya dilahirkan, saya masih disebut Cina’ (hlm 139). Tak hanya berhenti pada paparan, penulis juga mengulik aspek sejarah. Ia menyebut sejak abad ke-18 diadakan pemisahan antara mereka yang dianggap Cina dan mereka yang disebut pribumi. Hingga saat ini, rasialisme yang ditanamkan pemerintah kolonial Belanda masih mempunyai dampak luar biasa.
Berefleksi terhadap pandemi yang tengah melanda dunia kini, penulis pun mengetengahkan diskriminasi dalam konteks yang berbeda, yakni pada spesies lain. Lewat artikel ‘Virus Covid-19 dan Rasisme Kita’, ia mencermati bahwa ternyata manusia tidak hanya dihinggapi kesombongan pada sesamanya, bahkan pada makhluk lain pun masih pula jemawa.
“Mungkin dibutuhkan virus kecil untuk mengingatkan kita perlunya merenungkan kecenderungan kita untuk mendiskriminasi makhluk lain -baik yang terkait dengan jenis kelamin, etnis, usia, atau spesiesdan dampak dari sikap kita terhadap Bumi’, (hlm 201-202).
Manipulasi
Ramai-ramai soal komunis, penulis juga mencantum satu artikel berjudul ‘Komunis ala Kivlan Zen’. Bahkan hingga saat ini kalimat peringatan ‘Awas bahaya laten komunis!’ masih terdengar nyaring.
Seiring dengan seruan itu, banyak berlaku pelabelan komunis secara suka-suka. Sebutan komunis dan PKI cukup kerap terdengar di media sosial. Bahkan penulis buku ini juga sering dilabeli demikian.
Sayangnya, penyemat label tidak cukup punya pengetahuan. Bahkan kalaupun dibeber arti komunis ala mereka, jawabannya bisa membuat ngakak gulingguling. Sebagai contoh komunis itu ateis, komunis itu pengkhianat Pancasila, komunis itu kapitalis.
Kecupuan pengetahuan soal komunis baginya memang disengaja oleh para elite. Definisi komunis dibuat kacau-balau sehingga masih banyak yang berteriak komunis tanpa tahu arti kata yang mereka teriakkan.
‘Jelas sekali, para elite politik ini tidak ada niat untuk mencerdaskan masyarakat karena mereka sudah tidak segan lagi untuk memanipulasi dan mempergunakan kemalasan rakyat yang malas mengecek fakta’ (hlm 166).
Lanjut lagi dengan kekuatan politik yang hendak dibangkitkan dengan menjual narasi romantis masa lalu melalui slogan. ‘Jadi hanya mereka yang berpikiran jangka pendek saja yang akan percaya terhadap slogan Piye le, enak zamanku?’ tulis penulis dalam artikel ‘Piye Le Enak zamanku? Saat Rakyat Rindu Penjajah’ (hlm 179).
Menurut Soe, slogan itu patut dikritisi karena di dalamnya terdapat manipulasi yang sangat berbahaya dan menjerumuskan, yaitu kerinduan terhadap seorang koruptor dan bahkan salah satu pelanggar HAM terbesar. Hal serupa yang sempat terjadi dalam sejarah Indonesia saat baru saja merdeka.
Pembahasan Tuhan dan agama juga menjadi bagian menarik dalam buku ini. Salah satunya dalam artikel ‘Penodaan: Agama dan Tuhan yang mana?’. Salah satu kutipannya berbunyi, “Bila agama diturunkan demi kebaikan umat manusia, mengapa manusia menjadi tidak manusiawi karena alasan agama? Mereka mengusik kelompok yang dianggap tidak sepaham, walau kelompok ini tidak pernah mengganggu
mereka. Ajaran agama yang tidak memanusiakan manusia adalah ajaran yang patut dicurigai’ (hlm 227).
Sekelumit dari bagian pemungkas, ada artikel berjudul ‘Seandainya Hawking Lahir di Indonesia’. Jika saja ilmuwan kenamaan Stephen Hawking lahir di Indonesia, mustahil ia menjadi Hawking yang selama ini dikenal dunia.
Pasalnya, perawatan medis di Indonesia masih terbatas. Masyarakat masih belum siap menerima sosok seperti Hawking yang ateis. Bila mencari artikel yang berbincang soal seks, ada beberapa judul yang menarik, seperti ‘Feminisme: Antara Keharusan dan Pilihan’, ‘Aborsi: “Pro-life” atau “Pro-Choice”?’, ‘Luna Maya dan Ariel: Pendidikan Seks untuk Indonesia’, dan ‘Bahaya Pengutukan
Seks Bebas’.
Di satu artikel yang disebut belakangan, Soe Tjen yang juga seorang novelis dan komposer mempertanyakan pendefinisian seks bebas. Ia bukan hendak memungkiri adanya bahaya seks bebas yang memang menakutkan, melainkan mendudukkannya secara tepat. Selama ini, perempuan yang jadi korban.
‘Tetapi, pengutuk an akan segala bentuk seks bebas dan pelarangan kolot akan seks juga menimbulkan risiko lain yang akan dibahas’, (hlm 8). Kumpulan artikel di buku ini bisa jadi akan mendobrak wacana beku nan kaku yang selama ini menjangkiti sebagian masyarakat.
Tak dapat disangkal, buku ini memang ditulis dengan sudut pandang perlawanan. Jangan harap mendapat sesuatu yang mapan di dalamnya. Sebagai pemikir, Soe Tjen Marching telah memilih jalan feminisnya. Baginya, pilihan perempuan bisa tak terbatas dan tak terduga. Feminisme bukanlah pemaksaan bermacam keharusan. Ia (feminisme) membuka kesempatan, ia membebaskan. (M-2)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved