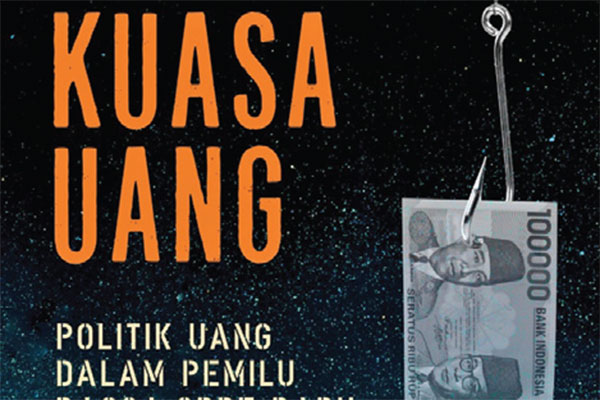Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
 Kumpulan Berita DPR RI
Kumpulan Berita DPR RI
BERBINCANG tentang kuasa uang dalam pemilihan umum (pemilu), tentu sudah bukan rahasia lagi.
Indonesia ialah sebuah contoh sempurna. Pemilu nasional maupun daerah menjadi lahan basah bagi jual-beli suara. Politik uang mendominasi strategi kampanye elektoral di Indonesia.
Demokrasi elektoral Indonesia dikorupsi oleh praktik jual-beli suara. Serangan fajar, istilah itu sering muncul saat penyelenggaraan pemilu. Beberapa hari sebelum pencoblosan, bahkan beberapa jam, tim sukses partai ataupun calon akan berkeliling ke rumah-rumah.
Diam-diam, mereka membagikan bingkisan berupa amplop atau sembako. Harapannya agar masyarakat memilih partai atau calon tertentu. Klientelisme, begitu istilah yang disematkan pada praktik tersebut.
Istilah itu merujuk pada pertukaran barang dan jasa untuk dukungan politik. Klientelisme dianggap sebagai penghalang utama bagi terlaksananya pemilu demokratis. Malapraktik elektoral itu ternyata tak hanya menonjol dalam pemilu legislatif di tingkat nasional, tetapi juga dalam pemilihan kepala daerah.
Bahkan, sedikitnya sepertiga pemilih di seluruh pelosok Indonesia terpapar oleh praktik klientelisme. Rata-rata tingkat politik uang di dunia ialah 14,22%. Indonesia berada di tiga besar negara dengan intensitas politik uang tertinggi Uganda (41%), Benin (37%), dan Indonesia (33%). Itulah yang menjadikan Indonesia layak dikaji dalam disiplin kajian politik uang.
Sayangnya, sebagian besar teori politik tentang pembelian suara dan pembelian partisipasi pemilih didasarkan pada pengalaman Amerika Latin. Akibatnya, banyak teori politik uang mengasumsikan bahwa partai adalah penentu cara dan proses pendistribusian uang.
Buku Kuasa Uang; Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru karya Burhanuddin Muhtadi ini justru menghadang teori tersebut dengan studi politik uang di Indonesia. Di Indonesia, kandidat peroranganlah yang melakukan operasi jual-beli suara.
Hal itu disebabkan persaingan intrapartai sangat ketat sehingga para kandidat melihat rekan-rekan separtai sebagai ancaman utama dalam meraih mimpi terpilih menjadi wakil rakyat. Akhirnya, para kandidat dipaksa bergantung sepenuhnya pada jejaring pribadi ketimbang mesin partai.
‘Ibarat Perang Baratayuda, pemilu tak ubahnya Kurukshetra yang menjadi medan pertarungan sesama saudara satu partai dengan uang sebagai senjata pemungkasnya’ (hlm 307). Selain itu, Muhtadi juga menganulir pendapat bahwa pemilih yang lebih berpendidikan cenderung tidak terlibat dalam pembelian suara. Ia mengungkapkan, dalam kasus Indonesia, tinggi-rendahnya tingkat pendidikan tidak membuat perbedaan signifikan dalam hal pengalaman ditawari politik uang.
Hal mengejutkan yang lain ialah tidak signifikannya faktor kemiskinan. Pemilih miskin dianggap lebih rentan terhadap praktik politik uang. Sekali lagi, di Indonesia, pembelian suara tidak memiliki hubungan signifikan dengan kemiskinan. Demikian pula, politik uang di Indonesia tidak memiliki pola perbedaan yang signifikan antara daerah perdesaan dan perkotaan. Selain itu, keterlibatan dalam organisasi sosial tidak membuat perbedaan dalam hal kemungkinan warga negara terpapar politik uang atau tidak (hlm 127).
Menariknya lagi, sasaran politik uang ternyata lebih menyasar pemilih partisan daripada pemilih nonpartisan. Loyalis partai malah cenderung menjadi target operasi pembelian suara. Sederhananya, makin dekat seorang individu dengan suatu partai, makin besar kemungkinan dia terpapar pembelian suara. Meskipun demikian, insentif material itu justru jatuh ke tangan para pemilih mengambang.
Sebagian besar pembelian suara malah terjadi di kalangan pemilih yang belum memutuskan. Hal itu juga seturut dengan fakta bahwa jumlah pemilih loyalis relatif kecil. Tingkat agregat kedekatan pemilih terhadap partai (party ID) di Indonesia relatif kecil, hanya 15% orang Indonesia yang merasa dekat dengan sebuah partai.
Kurang efektif
Buku ini juga mengetengahkan efektivitas politik uang terhadap pilihan suara hanya dalam kisaran 10%. Kecil memang. Namun, dalam konteks sistem proporsional terbuka, angka itu lebih dari cukup bagi banyak calon mendapatkan kemenangan.
Rata-rata margin kemenangan secara nasional antara yang menang dan rekan sesama partai yang kalah hanya 1,65%. Inilah yang menjelaskan mengapa politisi begitu antusias mengejar politik uang meskipun tingkat kebocorannya sangat tinggi.
Kendati demikian, mengejar kemenangan dengan margin tipis bukanlah satu-satunya alasan para kandidat masih terlibat dalam pembelian suara. Dilema tahanan, atau tertahan dan ikut arus dengan pola yang selama ini terjadi, menawarkan jawaban potensial tentang penyebab praktik pembelian suara terjadi secara luas di Indonesia. Akibat disengat kekhawatiran tinggi bahwa lawan mereka akan bagi-bagi amplop dan hadiah, para kandidat kemudian merasa berkepentingan untuk masuk dalam gelanggang jual-beli suara.
‘Setiap kandidat mungkin diuntungkan jika tidak ada satu pun politisi yang membeli suara. Namun, jika ada satu orang saja yang membelot dan kemudian melakukan operasi politik uang, semua kandidat yang lain akan kalah’ (hlm 310).
Hal ini sesuai dengan narasi yang berkembang di antara para kandidat dan tim sukses bahwa meskipun membeli suara sering tampak secara objektif tidak efisien, taktik semacam itu masih relatif lebih efi sien daripada strategi elektoral yang lain.
Kesimpulannya, penulis memberi tiga catatan terkait maraknya praktik jual-beli suara. Pertama, pembelian suara sebagai fungsi dari margin kemenangan yang ketat. Kedua, politisi terperangkap dalam dilema tahanan . Ketiga, persepsi pentingnya pembelian suara dalam
menggerakkan suara ketimbang strategi-strategi elektoral yang lain. (M-4)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved