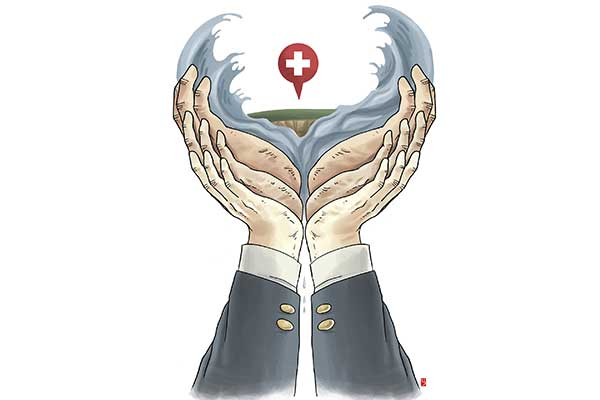Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
 Kumpulan Berita DPR RI
Kumpulan Berita DPR RI
SAMPAI saat ini, belum ada teknologi ataupun negara yang berhasil memprediksi kejadian gempa bumi dengan tepat dan akurat. Negara kita merupakan kepulauan yang terbentuk akibat dari tumbukan lempeng-lempeng tektonik aktif, yaitu lempeng Samudra Indo-Australia dan lempeng Samudra Pasifik, yang menumbuk atau menunjam masuk ke bawah lempeng benua Eurasia.
Tumbukan-tumbukan lempeng inilah yang mengakibatkan terjadinya gempa bumi, ataupun patahan-patahan batuan. Gempa bumi dapat pula terjadi pada zona patahan batuan tersebut. Gempa bumi yang terjadi pada dasar laut di sekitar zona tumbukan lempeng, ataupun pada patahan di dasar laut dengan magnitudo yang kuat, umumnya lebih dari 7 sebagai akibat pergerakan patahan dengan pergeseran relatif ke arah vertikal, dapat mengakibatkan terjadinya tsunami.
Karena kejadian gempa bumi masih belum dapat diprediksi dengan tepat dan akurat, kapan kejadian tsunami juga belum dapat dipastikan dengan tepat. Lalu, bagaimanakah kita harus menyikapi potensi kejadian gempa bumi, ataupun tsunami, yang bersifat merusak dan mematikan dalam kondisi yang tidak pasti kapan terjadinya? Inilah tantangan yang dihadapi BMKG dalam menjalankan UU Nomor 31 Tahun 2009 untuk dapat memberikan layanan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami demi mewujudkan zero victims apabila bencana tersebut terjadi.
Strategi mitigasi
Beberapa ahli kebumian dan kegempaan di Indonesia sudah mampu memetakan zona-zona yang rentan mengalami gempa bumi berdasarkan sebaran zona tumbukan lempeng tektonik yang ada di dasar laut ataupun sebaran patahan aktif yang berada di laut dan di darat.
Para pakar yang tergabung di dalam Pusat Studi Gempa Bumi Nasional (Pusgen) pada 2017 telah merilis buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia Tahun 2017 yang berhasil mengidentifikasi adanya 13 zona tumbukan lempeng (zona megathrust) dan 295 patahan aktif.
Zona tumbukan dan patahan aktif inilah yang menjadi dasar pertimbangan BMKG dalam menindaklanjuti hasil kajian tersebut untuk melakukan mitigasi. Zona itu merupakan zona yang berpotensi sebagai sumber terjadinya gempa bumi. Oleh karena itu, BMKG sejak 2019 mulai merapatkan jaringan sensor-sensor pendeteksi gempa bumi, yang menghadang zona megathrust dan mengepung patahan-patahan aktif tersebut.
Sejumlah 176 sensor yang terpasang sejak 2008 telah ditambah menjadi 411 pada 2020. Sensor-sensor inilah yang secara otomatis mendeteksi dan mengirimkan data ke sistem pemrosesan yang diperkuat dengan superkomputer dan kecerdasan artifisial, yang berada di BMKG Pusat di Jakarta, dengan back-up BMKG Denpasar sehingga dapat diketahui posisi pusat gempa bumi beserta kedalamannya, magnitudonya, dan potensi dalam menimbulkan tsunami. Dengan demikian, peringatan dini tsunami dalam waktu 3 sampai 4 menit setelah kejadian gempa bumi dapat disampaikan tersebar ke masyarakat melalui BPBD, media, dan berbagai kanal komunikasi.
Dalam kondisi ketidakpastian, BMKG melakukan mitigasi dengan pendekatan kajian ilmiah dengan mengolah lanjut hasil kajian ilmiah oleh para pakar untuk menyusun peta potensi bahaya tsunami yang menunjukkan potensi ketinggian dan waktu tiba tsunami pada suatu daerah pantai tertentu.
Peta bahaya tsunami ini sengaja dihitung berdasarkan skenario terburuk yang mungkin terjadi di suatu wilayah. Sebagai contoh, untuk wilayah pantai selatan Jawa Timur, berdasarkan temuan Pusgen 2017, potensi terburuk kejadian gempa bumi di lepas pantai selatan Jawa timur ialah berkekuatan 8,7.
Dari hasil pemodelan, dapat diperoleh informasi terkait dengan potensi ketinggian gelombang tsunami yang beragam, dengan waktu tiba tsunami yang juga beragam di wilayah pesisir Jawa Timur. Antara lain di pantai Kabupaten Trenggalek dengan potensi ketinggian tsunami 26-29 meter dan waktu tiba 28-31 menit serta Kabupaten Pacitan dengan potensi ketinggian tsunami 25-28 meter dan waktu tiba 26-29 menit. Lalu, pantai selatan Banyuwangi dengan potensi ketinggian tsunami 24-27 meter dan waktu tiba 21-24 menit serta Kabupaten Tulungagung dengan potensi ketinggian tsunami 24-27 meter dan waktu tiba 27-30 menit.
Selanjutnya, Kabupaten Blitar dengan potensi ketinggian tsunami 19-22 meter dan waktu tiba 20-24 menit, Kabupaten Jember dengan potensi ketinggian tsunami 19-22 meter dan waktu tiba 24-27 menit, serta Kabupaten Malang dengan potensi ketinggian tsunami 17-20 dan waktu tiba 21-24 menit. Juga, Kabupaten Lumajang dengan potensi ketinggian tsunami 13-16 meter dan waktu tiba 23-26 menit, pantai timur Banyuwangi dengan potensi ketinggian tsunami 4-7 meter dan waktu tiba 45-48 menit, serta Kabupaten Situbondo dengan potensi ketinggian tsunami 1-3 meter dan waktu tiba 76-79 menit.
Langkah mitigasi
Peta bahaya tsunami dengan skenario terburuk ini penting untuk diterapkan sebagai referensi dalam langkah mitigasi selanjutnya, yaitu untuk menetapkan zona aman sebagai tempat evakuasi sementara, beserta jalur evakuasinya.
Selain tempat dan jalur evakuasi, perlu pula disiapkan sarana dan prasarana penunjang evakuasi, seperti halnya rambu-rambu yang jelas untuk menunjukkan arah evakuasi, kondisi jalur evakuasi yang layak, aman, dan mudah dilalui, serta jembatan penyeberangan yang kuat terhadap guncangan gempa dengan magnitudo 8,7 apabila jalur evakuasi tersebut melalui sungai. Juga, tempat evakuasi yang memadai baik dari segi daya tampung ataupun kekuatan bangunan. Termasuk, fasilitas tangga atau jalan untuk naik ke atas tempat tersebut.
Bahkan, perlu pula dipastikan peralatan sistem peringatan dini, yang terpasang di BPBD/ Pusdalops, serta sirene peringatan dini dan jaringan komunikasinya beroperasi dengan layak untuk mewujudkan peringatan dini yang cepat dan tepat.
Untuk menjaga keandalan sistem dan peralatan tersebut di daerah, khususnya di BPBD/ Pusdalops, perlu dilakukan pengecekan rutin tiap minggu/ tiap bulan dan BPBD/ Pusdalops harus buka 24 jam setiap hari, untuk memastikan adanya petugas jaga, yang siap memencet sirene saat peringatan dini dari BMKG disampaikan sewaktu-waktu.
Berdasarkan informasi dari BNPB, terdapat 158 sirene yang telah terbangun oleh BNPB, yang dihibahkan ke daerah. Akan tetapi, 100 di antaranya telah rusak dan perlu segera diperbaiki dan diganti. Saat ini BMKG juga sedang menyiapkan penggantian 11 sirene, dengan teknologi tepat guna, produk dalam negeri. Selain sirene, dapat pula diterapkan peralatan tradisional, seperti kentongan dan radio komunitas.
Tas siaga bencana, yang berisi kelengkapan dasar untuk pertahanan keselamatan diri selama evakuasi, misalnya kotak P3K berisi obat-obatan, masker, hand sanitizer dan sarung tangan. Juga, makanan dan minuman untuk asupan pascabencana minimal tiga hari, handphone dan charger untuk memberi informasi, dan mencari bantuan. Lalu, dokumen pribadi, uang cash bekal untuk tiga hari, pakaian lengkap minimal untuk tiga hari, senter dan baterai tambahan, peluit untuk meminta pertolongan saat darurat, serta, radio portabel sebagai sumber informasi, setelah bencana, perlu selalu disiapkan, di tempat yang mudah terjangkau di dalam rumah saat evakuasi harus dilakukan.
Kesiapan masyarakat perlu terus ditingkatkan dengan literasi untuk peningkatan pemahaman dan kesadaran serta latihan rutin minimal tiap bulan untuk peningkatan keterampilan dalam mengevakuasi diri agar masyarakat dapat secara terampil/ cekatan dalam merespons peringatan dini yang bersumber dari BMKG dan disampaikan melalui BPBD setempat.
Kesiapan masyarakat ini harus terus ditingkatkan baik secara formal ataupun informal. Secara formal, dapat melalui kegiatan di sekolah ataupun secara ekstrakurikuler melalui kegiatan kepramukaan. Bahkan, secara mandiri dapat pula dilakukan sambil berolahraga (gerak jalan atau joging) ataupun berekreasi.
Selain itu, peta bahaya tsunami perlu diterapkan dalam menyempurnakan penataan ruang daerah rawan tsunami ataupun dalam perencanaan pengembangan wilayah. Kelestarian lingkungan daerah pesisir rawan tsunami juga perlu dijaga agar barrier pertahanan alamiah di sepanjang pantai, seperti mangrove, gumuk pasir, dan hutan pantai harus tetap terjaga, jangan sampai rusak ataupun ditambang.
Seluruh langkah mitigasi di atas perlu didukung dengan tersusunnya rencana kedaruratan beserta standard operating procedure (SOP)-nya, yang setiap waktu secara rutin harus diuji coba melalui latihan-latihan. Keterlibatan tim siaga bencana, yang sudah terbentuk di desa-desa sangat penting untuk berperan sebagai motor penggerak keberlanjutan langkah-langkah mitigasi tersebut.
Komitmen dari pemerintah/ pimpinan desa, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi mutlak diperlukan untuk menjamin terlaksananya langkah-langkah mitigasi ini secara berkelanjutan. Dengan berkelanjutannya langkah mitigasi untuk menyiapkan keselamatan masyarakat di daerah rawan, budaya selamat dari bencana dapat terpupuk secara berkelanjutan dan akhirnya dapat segera terwujud budaya selamat dari bencana.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved