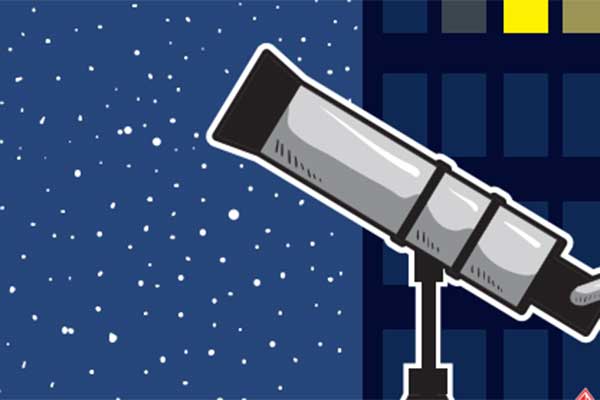Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
 Kumpulan Berita DPR RI
Kumpulan Berita DPR RI
SEBELUM teropong itu menangkap sosok bidadari yang melepas pakaian satu demi satu, lebih dulu dia kerap dihajar oleh kekecewaan sebab tak bisa menangkap sekelebat cahaya bintang.
Cahaya alit yang mungkin saja pudar, tetapi kerap membuatnya yakin bahwa di langit ada kehidupan. Pada ulang tahun keenamnya, Ayah yang kemudian tak kembali sebab ditelan kematian membelikannya sebuah teropong.
Harga teropong sungguh mahal untuk hadiah anak yang belum juga bisa mengartikan cinta dan ulang tahun. “Mengintip langit sama saja mengintip masa depan,” kata Ayah.
Ibu menimpuk punggung Ayah dengan gulungan koran. Bicara sama anak kecil kenapa harus tinggi-tinggi, kata Ibu lumayan kencang. Dia tidak begitu tertarik keributan kecil kedua orangtuanya, dia telah tersihir oleh tabung dengan kaki penyangga mirip trisula itu.
“Dengan ini kamu akan tahu surga ada di mana.” Kali ini pukulan tangan ibunya lebih keras tanpa perlu koran.
Matanya bersinar lebih terang dari lilin ulang tahun berjumlah enam di atas keik cokelat. Di kepalanya muncul adegan-adegan yang entah bagaimana bisa tersambung dari banyak dongeng yang kerap dibacakan sebelum tidur.
Bidadari yang berselendang tipis warna-warni, kemudian turun dari salah satu surga, kedatangannya bergelimang cahaya bintang, mandi di sebuah telaga tersembunyi, dan dia mengintip dari lantai apartemennya menggunakan teropong itu.
“Kamu mikirin apa? Buruan make a wish!” Ibunya menyenggol lamunannya.
Sebelum lilin ulang tahun padam, dia berdoa agar kelak di salah satu bintang dia bisa bertemu yang dia inginkan. Surga dan bidadari. Tiga bulan kemudian saat Ibu meraung-raung menerima telepon dari rumah sakit, dia tahu Ayah mungkin telah ada di salah satu bintang dan dia akan berusaha menangkapnya dengan teleskop.
Dan semenjak itu pula, dia tak henti-hentinya mencari dengan mata teropong. Setiap malam doanya terbang bersama angin yang membentur kaca apartemen. Hingga ulang tahunnya yang ketujuh sebulan lagi tiba, dia belum juga berhasil menangkap cahaya bintang.
Langit di kotanya lebih pekat dari kuah cumi hitam buatan Ibu. Kata Ibu, langit kotor penuh karbon dioksida. Ah, apa itu saja dia tidak tahu. Yang pasti, teleskop mahal hadiah ayahnya tak berdaya menyingkap pekat malam dan menangkap cahaya bintang.
Selepas membuat PR dan menyantap makan malam, dia lekas membawa teropong ke beranda apartemen. Mengarahkan moncong teropong ke langit. Tangannya yang mungil memutar-mutar kenop yang dia dan ibunya sendiri tak paham betul cara mengoperasikan, lebihlebih fungsinya.
Mata diletakkan di sisi yang lebih kecil berusaha mengintip dari celah tersebut. Gelap dan selalu pekat.
“Ibu, apa bintang hanya ada di buku?”
“Maksudmu?” tanya Ibu yang malam ini sibuk mengemas beberapa pakaian bekas layak pakai untuk disumbangkan.
“Bintangnya tidak ada. Susah ditangkap.”
“Kalau kamu tidak menemukan, bukan berarti tidak ada.”
Dia menelengkan kepala. “Bintang ada. Hanya langit Jakarta yang kotor. Coba sedikit lebih malam. Langit akan lebih bersih saat kendaraan-kendaraan sudah pada pulang,” Ibunya menjawab tanpa memandang wajah anaknya yang dua hari lalu memar sebab berulah di kelas olahraga. Dia menggosok memar yang mulai hilang dan denyut nyeri yang tipis mengedipkan matanya secara otomatis.
“Apalagi apartemen kita banyak cahaya. Makin susah teropongmu menangkap bintang.”
“Sebaiknya kutunggu sebentar,” bisiknya dan berjalan ke sofa tak jauh dari Ibunya yang masih bersila di tengah tumpukan baju bekas.
Seperti kebanyakan anak-anak, janji untuk bergadang hanya berujung kantuk dan tidur di sofa tengah. Pukul sepuluh malam, saat mungkin langit Jakarta mulai sedikit lebih jernih, dengkurnya halus terdengar.
“Hadeeeh! Kalau tidur, kenapa enggak gosok gigi dulu!”
Ibunya mengomel dan dibalas oleh gema suaranya sendiri. Saat hendak mengangkat anaknya yang tertidur, Ibu muntab. “Ini kenapa wajahmu! Pasti berkelahi lagi!”
Omelannya cukup keras seolah anaknya masih bisa menjelaskan duduk perkara. Semakin menjadi, saat tahu teropong masih teronggok di beranda, jendela kaca terbuka, dan buku-buku berserakan di meja.
“Kapan bisa istirahat kalau punya anak seorang saja sudah sedemikian melelahkan!”
Dalam bopongan Ibu, dia samarsamar mendengar percakapan ayahnya dengan seorang bidadari. Sebentar lagi teropong anakku akan menangkap cahaya bintang.
Langit Jakarta menjadi lebih jernih. Angka polusi udara Jakarta turun drastis. Semenjak langit tampak lebih biru dari biasanya, dia tak bisa lagi ke sekolah.
Ibunya 24 jam di rumah dengan laptop dan gawai tak pernah jauh. Dan ibunya mulai suka memotret langit-langit Jakarta di siang hari.
“Kita harus di rumah saja selama ada penyakit ini,” kata Ibu.
“Kenapa langit sekarang jadi lebih indah? Kenapa Ibu jadi suka memotret langit?”
“Kamu sama menjengkelkannya dengan ayahmu,” pandangan Ibu terpaku pada layar ponsel, mencerahkan dan mengatur saturasi dari hasil jepretannya.
“Di luar banyak orang sakit. Semua harus di rumah sampai penyakit itu pergi.”
Seharian dia membolak-balik buku tanpa ada satu kalimat yang berhasil masuk. Matanya bolakbalik melihat sepotong langit dari kotak jendela apartemen. Ingin dia membawa teropongnya ke beranda dan menangkap bintang di langit Jakarta. Meskipun langit jernih, apa ada bintang di tengah siang? Nanti petang, saat Ibu menyiapkan makan malam, dia akan membawa teropong itu dan menangkap bintang.
“Di rumah saja, bukan berarti main seharian. Ibu masih harus bekerja dan kamu harus belajar. Nonton televisi baru boleh setelah jam enam malam.”
Suara ibunya memantul. Seolah khawatir kalau dia yang mulai diam tiba-tiba merencanakan untuk tidak belajar dan menonton siaran lawak di televisi.
“Ibu PR-ku sudah selesai kubuat,” dia membawa buku latihan soal ke meja Ibu. Tak digubris, sebab tangan Ibu penuh. Satu menopang gawai yang menempel di telinga kiri sambil ber-iya-iya, sedangkan satunya memegang tetikus laptop.
Mata Ibu berkedip dan kepalanya mengangguk. Tanda dia tak boleh mengganggu Ibu. Dia ingin mendengar izin Ibu untuk berhenti belajar sehingga dia bisa gegas mengubek-ubek langit.
Setengah jam kemudian Ibunya merangkul dari belakang, “Kamu pintar, mandiri. Ibu waktu seusia kamu sudah disuruh mencuci sendiri dan menggembala sapi.”
Ibu tertawa kencang sambil mengelus rambutnya. Lagi-lagi hanya dinding yang menimpali dengan gaung yang tak kalah riuh.
“Ibu mau masak ayam goreng. Kamu mandi saja. Nanti kamu selesai mandi, ayam goreng Ibu sudah siap.”
Dia masih diam saja. Dia menarik-ulur kalimatnya agar dia bisa main sedikit lebih lama.
“Ibu, apa boleh aku main sebentar. Mandinya nanti habis makan saja.”
Biasanya Ibu akan marah. Tetapi menyaksikan dia yang hari ini begitu patuh sekaligus tekun membuat PR, ibunya luluh dan membuat senyum paling manis. Ibu mengangguk.
“Emang mau main apa? Sudah mau gelap juga.”
“Aku mau meneropong langit.” Alis Ibu mengerut.
“Mumpung langit sedang jernih. Aku mau meneropong langit.”
Ibunya tertawa lebih kencang. Elusan di kepala kini berganti dengan pelukan paling kuat, sampai dia tampak mulai menggapai-gapai susah bernapas.
“Ah, maafkan Ibu. Saking gemasnya Ibu sama kamu.” Keduanya bertatapan dan bungah.
Dia menyeret teropong besar hingga di beranda apartemennya. Matanya menempel pada sisi lebih kecil dan sisi besar itu diarahkan ke langit Jakarta yang masih saja bening meski sudah lewat pukul lima petang. Dia yakin betul kali ini bisa menangkap bintang.
Sebab langit Jakarta jernih. Sebab teropong pemberian ayahnya adalah teropong mahal. Sebab semua orang Jakarta sedang di rumah, seperti ibunya, dan mengagumi langit yang lebih biru dari hari-hari biasanya.
Suara minyak mendidih bertemu potongan ayam berbalut tepung. Wangi gurih daging ayam segar, bumbu instan, serta legit lemak minyak menguar di ruangan apartemen mereka. Dia tak menjauhkan sedetik pun mata dari teropongnya.
Dia mengubah-ubah posisi teropong. Tetapi hanya biru langit dan putih awan yang seperti segumpal permen kapas. Tidak ada bintang. Tidak ada bulan.
“Ibu, kenapa juga bintang belum ada?”
“Haaa!” Ibunya tidak begitu mendengar. Suara perkakas dapur dan bunyi minyak menghalau pertanyaan anaknya.
“Sebentar lagi selesai. Cepetan mandi. Habis itu makan bareng.”
“Apa bintang benar-benar ada? Langit Jakarta yang jernih saja tidak bisa menangkapnya,” dia berbisik pelan. Teropong masih berpindahpindah posisi.
“Mandi saja dulu!” suara Ibu kencang. Tak paham apa yang digumamkan anaknya. Hingga kemudian mata teropong itu menangkap sosok perempuan di seberang bangunan apartemennya.
Perempuan itu mungkin seumuran ibunya. Perlahan-lahan melepas baju. Tubuhnya siluet tertimpa cahaya terang dari jendela kaca. Dia tak menggeser satu senti pun teropong. Dia mengamati apakah dia sosok bidadari yang kata Ayah turun dari langit untuk mandi.
Perempuan di ujung sana tentu tak sadar sedang diawasi dari balik teropong. Dia tak berkutik hingga kemudian ibunya menghentak. “Kebiasaan! Kalau main lupa mandi! Mandi dulu!” sambil menariknya ke kamar mandi.
Malam belum begitu malam. Langit masih sedikit oranye. Ayam goreng, nasi putih hangat, serta tumis sawi putih terhidang di meja. Ibunya makan perlahan sambil menyahuti suara pembawa berita berbahasa Inggris di televisi. Dia belum selesai mengunyah gigitan ketiga.
“Apa Ayah ditemani bidadari?”
Seketika Ibu menghentikan kunyahan. Ruangan apartemen mendadak pengap. Paha ayam diletakkan. Pisau berdenting kena permukaan piring.
“Kenapa kamu tanya begitu?”
“Katanya orang meninggal akan tinggal bersama bidadari.”
“Tidak semua tinggal bersama bidadari. Ayahmu diam termangu di langit memandangi kita.”
“Oooo...” dia tak melanjutkan pertanyaan. Ibunya kini beranjak dari kursi menuju kulkas mengambil air dingin dalam botol.
Sesungguhnya ingin sekali dia bercerita bahwa di ujung teropong perempuan mirip bidadari itu bersama laki-laki mirip ayahnya. Mereka bergelut, seperti yang sering dilakukan Ibu dengan kawan lelakinya.
“Langit Jakarta jernih. Apa bintang bisa kulihat malam ini, Ibu?”
“Mungkin.”
Keduanya sama-sama menatap sepotong langit Jakarta dari jendela kaca. (M-2)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved