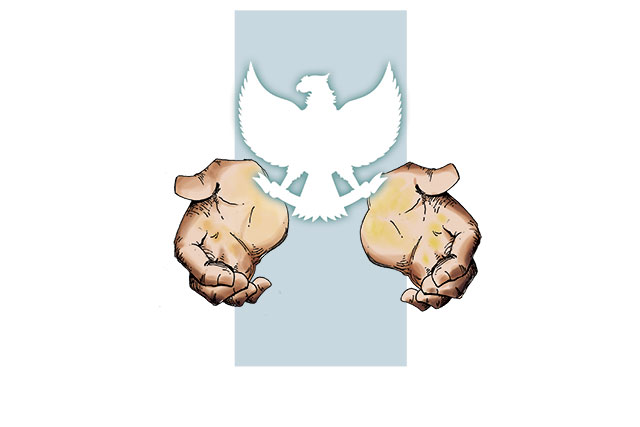Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
 Kumpulan Berita DPR RI
Kumpulan Berita DPR RI
KONTROVERSI kehadiran agama di ruang publik sampai saat ini tidak terlepas dari tema besar dalam sosiologi politik, perihal bagaimana merumuskan hubungan peran antara agama dan negara. Mungkinkah agama hidup dan berkembang tanpa negara? Atau sebaliknya, apakah sistem demokrasi bisa mewujudkan cita-citanya tanpa menghubungkan dirinya dengan agama?
Agama sebagai dasar prapolitik
Persoalan yang sedang mewarnai sosiologi politik di RI ialah dua kecenderungan yang sama-sama mendatangkan musibah bagi proses mengindonesia ke depan. Pertama, agama yang sedang mencari dasar pembenaran dan membangun poros kekuatan pada kekuasaan. Kedua, agama dimanfaatkan untuk memperkuat basis dukungan politik kekuasaan.
Hal pertama berbahaya karena agama bisa saja menindas dan mengambil alih ruang publik (titik pertemuan semua agama atau etnik sosial). Yang kedua juga berbahaya, karena entah sadar atau tidak, agama direndahkan kedudukannya untuk melayani hasrat kekuasaan.
Tentu mesti disadari bahwa negara Indonesia –dengan segala fondasi ideal dan konstitusionalnya– tidak pernah bertentangan dengan doktrin agama apa pun, sejauh negara sanggup memenuhi kewajibannya untuk melayani hak-hak setiap warga negara.
Tidak ada dasar bagi agama-agama untuk menggantikan dasar dan filosofi kenegaraan. Pancasila dan UUD NRI 1945 adalah hasil rumusan dan refleksi bersama yang memuat sistem nilai yang sesuai dengan kondisi objektif bangsa kita.
Pancasila ialah jejak budaya sekaligus tonggak penyangga. Sehingga suku-suku di nusantara bisa bersatu dan membentuk suatu negara kedaulatan bersama. Dalam bahasa Yudi Latif, Pancasila ialah titik temu, titik pijak, dan titik tuju proses mengindonesia.
Pancasila ialah filsafat, arkhe, prinsip kenegaraan yang menyatukan dan menjadi titik temu semua keberagaman kultural, agama serta etnik. Hal yang perlu terus diwacanakan ialah bagaimana menerjemahkan prinsip dan nilai-nilai Pancasila dalam ruang sosial keindonesiaan, dalam rumusan kebijakan dan perilaku sosial sehari-hari.
Dengan kata lain, tugas bangsa dan negara sekarang ialah memberi isi dan bobot makna kepada Pancasila sehingga dapat dijadikan filosofi, prinsip, sekaligus rumusan bersama untuk memberi jawaban atau solusi konkrit terhadap semua persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Kesadaran di atas sekaligus menegaskan, bahwa Indonesia ini bukan milik satu agama, satu suku atau etnik tertentu saja. Maka, tak bisa dibenarkan dengan mengacu pada latar sejarah keindonesiaan jika Indonesia saat ini hendak dibangun lagi atas dasar nasionalisme etnik atau agama.
Indonesia ialah rekam jejak sebuah proses humanisasi. Perihal bagaimana orang-orang di Nusantara berjuang untuk meningkatkan derajat kemanusiaan mereka dari belenggu kolonialisme. Api kesadaran untuk merdeka bukan didorong oleh perjuangan karena kesamaan etnik atau agama, melainkan bertolak dari kesadaran untuk membebaskan dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan yang tercabik oleh penjajahan. Dasar perjuangannya melampaui kepentingan sektoral keagamaan.
Mesti disadari, kesadaran untuk melepaskan kemanusiaan dari penindasan-penjajahan ialah bagian dari kesadaran religius suku-suku yang berkembang di Nusantara. Artinya, terlepas dari agama apa pun, dan apa pun namanya, perjuangan untuk merdeka dan membentuk Indonesia sebagai milik bersama juga didorong oleh kesadaran religius.
Pada titik ini, kita tidak bisa mengabaikan peran agama-agama untuk membangkitkan kepekaan humanistis suku-suku di Nusantara dan membentuk satuan politis yang berdaulat. Agama menjadi titik inspirasi dan kekuatan prapolitik yang mendorong terbentuknya Indonesia. Yaitu, ruang bersama di mana nilai-nilai kemanusiaan dapat dihargai dan dilindungi oleh negara. Sebab itu, proses mengindonesia sampai saat ini dan ke depannya, tidak boleh mengabaikan catatan sejarah masa lalu.
Kesadaran kebangsaan
Memang, kita sedang mengalami fase defisit pemahaman dan kesadaran kebangsaan karena kekuatan-kekuatan ekonomi-politik ekstraktif sedang melilit proses-proses sosial di tengah masyarakat. Epiphenomenon dari defisit kesadaran itu muncul dalam sikap-sikap penolakan terhadap keberagaman, intoleransi, dan diskriminasi sosial-politik. Atau pada bagian awal ulasan tadi, kita sedang mengalami kesulitan dan masalah serius bagaimana merumuskan relasi seharusnya antara agama dan negara.
Ada dorongan kuat menghidupkan komunitarianisme berbasis etnik atau agama. Serta dorongan politik kekuasaan yang memperalat basis-basis kekuatan agama. Yang pertama menghasilkan semangat nasionalisme etnik atau agama, yang kedua justru merendahkan tujuan luhur agama.
Agama hendaknya menyalakan kesadaran untuk mendorong proses-proses politik demokrasi bisa berjalan secara adil dan berkeadaban. Dengan kata lain, agama mesti sanggup membangkitkan kesadaran warga untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi secara penuh.
Itu berarti, agama membangkitkan kesadaran kewargaan yang kuat, terlibat mematangkan kesadaran mengindonesia sebagai negara berdaulat. Bahkan, dalam kajian-kajian negara sekuler sekalipun, agama tetap menjadi kekuatan penyangga etika dan moral kenegaraan.
Dengan demikian, jelaslah bahwa agama tidak bertentangan dengan negara, melainkan keduanya dapat membentuk sebuah relasi yang saling mengokohkan. Agama memperkuat kesadaran bernegara. Sebaliknya, negara memastikan agama-agama hidup berkembang secara damai satu sama lain.
Agama tidak boleh diperalat untuk kepentingan politik. Tujuan agama ialah mengarahkan manusia kepada kebaikan tertinggi (bonum maximum).
Oleh karena itu, ketika agama dijadikan kuda tunggangan politik kepentingan, demikian menurut sosiolog Ignas Kleden, kita sedang merendahkan martabat agama sebab agama diturunkan derajatnya untuk melayani kepentingan kekuasaan. Kesadaran ini mesti diinsafi dan disadari oleh semua agama. Terutama oleh para pemuka agama dan para politisi supaya tidak merusak citra agama-agama.
Sedapat mungkin agama mengambil jarak yang kritis sekaligus berdialektika dengan negara supaya tidak terkontaminasi oleh tujuan-tujuan kepentingan politik praktis. Agama mengambil jarak kritis sekaligus memberikan pencerahan kepada bentuk-bentuk penyelenggaraan kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi serta bertentangan dengan paham-paham kebangsaan.
Pada titik ini, agama dapat berperan sebagai rujukan kritis untuk mengoreksi ideologi negara, tapi bukan untuk mendirikan negara agama. Prinsip-prinsip universal kemanusiaan yang diakui oleh semua agama dapat dijadikan basis perjuangan bersama bagi semua agama untuk terus mengkritisi bentuk-bentuk operasional kekuasaan negara.
Akan tetapi, tatkala agama melayani kepentingan kekuasaan, agama dijadikan ideologi perjuangan, yang dalam sejarah perkembangannya bisa melahap nilai-nilai kemanusiaan dan berwajah radikal. Nah, pada hemat saya, cara beragama seperti ini perlu dihindari, karena tidak sesuai dengan corak kultural Indonesia. Untuk itu, masyarakat perlu memiliki pandangan keagamaan yang lebih terbuka terhadap perbedaan dan menghargai kehadiran Allah dalam berbagai bentuk sistem keyakinan yang lain.
Untuk konteks khusus Indonesia, negara perlu berdialog dengan agama-agama. Merupakan sesuatu yang unik dan istimewa sekaligus menyimpan potensi yang menghancurkan jika tidak dirumuskan secara proporsional dan setara. Dialog itu bisa dalam lintas institusi, komunitas-komunitas sosial, tapi juga bisa lintas masyarakat untuk membuka tirai prasangka yang sempit.
Radikalisme bertumbuh seiring dengan kesempitan kesadaran dan pemahaman terhadap perbedaan. Sebaliknya setiap pemeluk yang dibentuk oleh pengalaman lintas batas cenderung lebih terbuka dan toleran terhadap sesama yang berbeda keyakinan.
Sejalan dengan itu, kesadaran kebangsaan lebih terbuka, dan melihat keindonesiaan sebagai titik temu dan ruang peleburan yang membentuk harmoni sosial yang damai. Agama mesti mendorong setiap pemeluk untuk menghargai perbedaan sosial dan mendorong perwujudan nilai-nilai demokrasi ke arah yang lebih matang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved